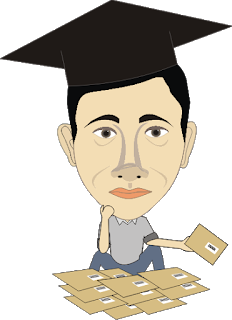Oleh: Susi Lestari, S.Pd.
Setelah berhasil memindahkan toga dari kiri ke kanan, lantas mau apa? Usai menggelar pesta perayaan wisuda sana-sini, lantas mau ke mana?
Pertanyaan di atas kerap berkelindan dibenak para lulusan sarjana pendidikan baru (fresh graduate). Ada yang menjawabnya dengan keberuntungan cepat mendapat pekerjaan sebagai guru di sekolah. Beberapa masih berjibaku mengirim berbagai formulir lamaran pekerjaan. Sebagian memilih berdesak-desakan di setiap acara job fair dengan peluh yang mengalir dan lantunan doa supaya bisa cepat kerja. Dan yang paling banyak tentu saja memilih jalan lain; menjadi pegawai bank, kerja serabutan, sales, atau mengurus berkas aplikasi pendaftaran beasiswa S2. Intinya, berusaha keras agar tidak menjadi penganggguran.
Seseorang yang memilih jalan untuk menjadi sarjana pendidikan, tanpa peduli bahwa peluang menjadi penganggurannya lebih banyak dibandingkan menjadi guru itu sendiri, adalah pilihan naif. Setiap tahunnya, kuota penerimaan guru di Indonesia sekitar 40.000 orang. Jumlah itu tidak sebanding dengan jumlah lulusan sarjana pendidikan yang bisa mencapai ratusan ribu orang.
Persoalan lulusan baru sarjana pendidikan tidak berhenti di fakta itu saja. Kalau diterima menjadi guru yang belum PNS pun, gaji yang didapatkan hanya sebanding dengan ongkos jalan. Biaya mengajar, membimbing, mendidik, membuat kreasi media pembelajaran, biaya makan, dan biaya-biaya lain, mau tak mau keluar dari kantong sendiri. Masih tetap mau jadi guru? Baiklah. Anggap saja, kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
Tetapi, di era milenia seperti sekarang ini, siapa yang sanggup berlama-lama menjadi pahlawan tanpa bintang kehormatan? Tidak ada. Usaha pun berlanjut: mengejar gelar PNS. Namun, sebagaimana lazimnya lowongan pekerjaan di Indonesia, benteng lowongan PNS sangat sulit untuk ditembus. Biasanya yang masuk “satu banding seribu”. Orang yang masuk kategori “satu”, kalau tidak pintarnya kebangetan, uangnya banyak, ya, biasanya dipersepsi punya banyak koneksi. Itulah Indonesia. Lantas, kalian masih mempertahankan diri untuk tetap menjadi guru. Baiklah, ada saran yang cukup konkret yang bisa diberikan, yakni menantang para sarjana pendidikan yang baru lulus.
Seragamisasi, Transparasi, dan Distribusi
Di dalam sebuah forum diskusi, seorang pemantik bertanya, “Apa yang akan kalian lakukan di bawah umur 30 tahun?”
Para peserta diskusi terdiam. Tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Tak lama seseorang pria dewasa tanggung dengan topi hitam yang menutupi rambut di kepalanya mengangkat tangan. “Membangun yayasan dan menjadi kepala sekolah.”
Orang-orang yang berada di dalam forum sontak menunjukkan reaksi yang berbeda-beda. Ada yang terkekeh, menganggukkan kepala, bahkan ada yang mengerutkan kening, “Ngomong apa orang ini?”
Sindrom yang kerap dialami oleh para lulusan baru adalah ketidakberanian untuk memulai sesuatu yang berasal dari masalahnya sendiri. Sulit mendapat pekerjaan dan minimnya lowongan guru dianggap sebagai masalah pemerintah yang harusnya menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Padahal semestinya tidaklah demikian, seorang sarjana pendidikan tidak boleh hanya menggerutu atau mencari kambing hitam. Seorang lulusan baru harus berani mengambil kesempatan dari hasil kepekaannya terhadap lingkungan sekitar. Seperti yang dilakukan oleh Ai Nurhidayat, pria yang ketika baru lulus sarjana memilih untuk menciptakan peluangnya sendiri.
Ai, pria tanggung yang pernah mencetuskan mimpi untuk menjadi kepala sekolah, saat ini telah menjadi kepala sekolah di sebuah yayasan. Sekolahnya bernama SMK Bhakti Karya Parigi “Sekolah Multimedia Ramah Budaya” di Pangandaran, Jawa Barat. Rasa muaknya terhadap sistem sekolah di Indonesia yang tak kunjung benar, membulatkan tekadnya untuk membangun sekolah berbasis multikultural.
Ai menyakini bahwa selama sekolah masih terus melakukan seragamisasi, Indonesia tidak akan bisa maju. Selama tidak ada transparasi, pendidikan di Indonesia hanya jadi ladang untuk memperkaya diri bagi segelintir orang. Dan selama distribusi guru dan siswa belum optimal, menyebar ke seluruh sudut terpencil Nusantara, tujuan Negara Indonesia seperti termaktub dalam alenia empat Pembukaan UUD 1945 “mencerdaskan kehidupan bangsa”, tidak akan pernah terlaksana. Itulah mengapa sarjana pendidikan yang baru lulus harus memilih melakukan perubahan di antara tiga aspek tadi: seragamisasi, transparasi, dan distribusi. Jika ketiga aspek tersebut tidak bisa dijangkau oleh para lulusan sarjana pendidikan yang baru, mulailah berpikir untuk tidak menjadi guru, karena menjadi “digugu lan ditiru” adalah pekerjaan berat.
Permasalahan yang sering muncul ke permukaan–terlebih akhir-akhir ini–adalah perbedaan yang menimbulkan persoalan, perdebatan, dan silang pendapat. Umat beragama yang berbeda saling intoleransi, klub olahraga fanatik saling baku hantam, atau politisi yang berbicara sembarangan tentang perbedaan. Kalau mencari akar semua masalah perbedaan di Indonesia, sehingga menciptakan keadaan yang demikian, jawabannya adalah: sekolah.
Bagaimana masyarakat Indonesia mau menghargai perbedaan, jika hal yang harus dilakukan ketika pertama kali masuk ke sekolah formal adalah harus tunduk pada segala hal yang diseragamkan? Membincang seragamisasi di sekolah, seperti seragam, fasilitas, nilai, ujian, dan segala tetek-bengek yang selalu harus disamakan seolah mengukuhkan anggapan “kebhinekaan di Indonesia hanya fatamorgana”. Sekolah harusnya mampu menampilkan kodrat Indonesia yang multikultural, yang berbeda-beda. Tetapi, kenyataannya non sense, hanya segelintir yang sudah menerapkannya di dalam sekolah, sedangkan yang belum? Inilah tantangan para sarjana pendidikan yang baru lulus.
Satu-satunya sektor di Indonesia yang alokasi anggarannya disebutkan secara gamblang adalah pendidikan. UUD 1945 mengamanatkan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20%. Alokasi yang sangat besar, bukan? Tetapi, bagaimana dengan penerapannya? Tidak ada yang benar-benar tahu. Transparansi ibarat candu di mata dunia pendidikan Indonesia, karena sekalinya dicecap akan membuat banyak orang ketagihan. Ketagihan untuk menggeledah. Maka, jangan heran, jarang ada sekolah yang terang-terangan mempublikasikan penggunaan anggaran sekolah (audit diri). Hal ini diperparah pula oleh ketakacuhan publik, sehingga kesan sekolah adalah lembaga pendidikan yang tertutup semakin lekat.
Aspek terakhir yang perlu ditangani dengan serius oleh para sarjana pendidikan yang baru lulus adalah distribusi guru. Jumlah guru di kota-kota besar sangat berlebih, sedangkan di daerah-daerah terpencil sangat kekurangan. Keadaan tidak merata tersebut, bisa segera terselesaikan, jika para sarjana pendidikan yang baru lulus “legawa” untuk menyingkirkan egonya dan mengabdi di mana pun, asal masih dalam pangkuan ibu pertiwi.
Maka, dari tiga aspek besar masalah pendidikan di Indonesia, kini giliran yang baru lulus, yang ingin cepat kerja, yang ingin memiliki gaji sesuai selera, selesaikan terlebih dahulu persoalan seragamisasi, transparasi, dan distribusi. Sehingga, tidak ada rumusnya masih menganggur saat ini!
Mari menantang ribuan para sarjana pendidikan yang baru lulus untuk menciptakan: sekolah tanpa seragamisasi, sekolah yang bertransparasi, dan sekolah yang distribusi siswa dan gurunya merata hingga pelosok negeri. Jika sosok Ai bisa melakukannya, mengapa kalian tidak?
*Alumnus Universitas Negeri Semarang