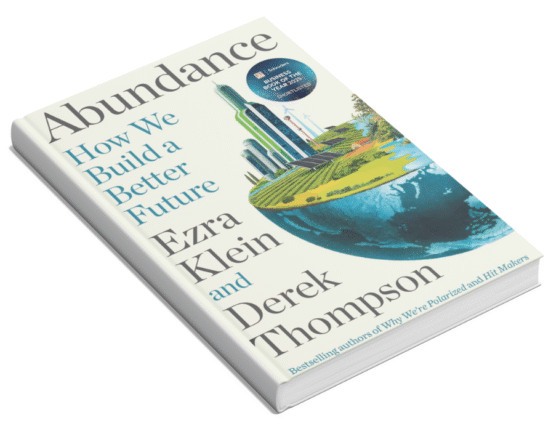|
| Sonia Gandhi dan kover buku Perempuan Panggung (Dok. Mia) |
Judul :
Perempuan Panggung
Perempuan Panggung
Pengarang :
Imam Budhi Santosa
Imam Budhi Santosa
Tahun terbit :
2007
2007
Penerbit :
Navila (viii+260 hlm: 18 cm)
Navila (viii+260 hlm: 18 cm)
ISBN :
979-950-376-0
979-950-376-0
Perempuan selalu menjadi
magnet menarik untuk dibawa dalam suatu cerita. Bagai sayur tanpa garam,
begitulah nasib sebuah cerita tanpa adanya taburan tokoh perempuan. Perempuan diulas
dari berbagai sudut kehidupannya. Menampakkan sekelumit cerita yang jarang
menjadi perhatian. Menggambarkan perjuangan perempuan memunculkan satu realita
bahwa perempuan bukan manusia kelas dua. Perempuan memiliki kehidupannya
sendiri, perjuangan, nilai, dan keunikannya. Tak pantas jika kemudian
membandingkan dengan laki-laki karena memang sudah berbeda. Menjadi setara
adalah ketika perempuan menempatkan dirinya sebagai perempuan, bukan ingin
menjadi seperti laki-laki.
magnet menarik untuk dibawa dalam suatu cerita. Bagai sayur tanpa garam,
begitulah nasib sebuah cerita tanpa adanya taburan tokoh perempuan. Perempuan diulas
dari berbagai sudut kehidupannya. Menampakkan sekelumit cerita yang jarang
menjadi perhatian. Menggambarkan perjuangan perempuan memunculkan satu realita
bahwa perempuan bukan manusia kelas dua. Perempuan memiliki kehidupannya
sendiri, perjuangan, nilai, dan keunikannya. Tak pantas jika kemudian
membandingkan dengan laki-laki karena memang sudah berbeda. Menjadi setara
adalah ketika perempuan menempatkan dirinya sebagai perempuan, bukan ingin
menjadi seperti laki-laki.
Begitulah perempuan
bernama Suciati yang menjadi tokoh utama dalam novel Perempuan Panggung karya Imam Budhi Santoso. Suci menjadi gambaran
bahwa perempuan hebat tak selalu harus berusaha menyetarakan dirinya dengan
ikut menjadi seperti laki-laki. Feminisme yang digembar-gemborkan Barat
nyatanya tak lebih dari konsep pikir yang keliru, radikal, dan tak sesuai
dengan nilai Timur. Di sini, Imam—meski laki-laki—menghadirkan perspektif baru
dalam memandang perempuan sebagai perempuan, makhluk setara dengan laki-laki
tanpa harus menjadi seperti laki-laki.
bernama Suciati yang menjadi tokoh utama dalam novel Perempuan Panggung karya Imam Budhi Santoso. Suci menjadi gambaran
bahwa perempuan hebat tak selalu harus berusaha menyetarakan dirinya dengan
ikut menjadi seperti laki-laki. Feminisme yang digembar-gemborkan Barat
nyatanya tak lebih dari konsep pikir yang keliru, radikal, dan tak sesuai
dengan nilai Timur. Di sini, Imam—meski laki-laki—menghadirkan perspektif baru
dalam memandang perempuan sebagai perempuan, makhluk setara dengan laki-laki
tanpa harus menjadi seperti laki-laki.
Suci adalah mahasiswa
Fakultas Hukum sebuah universitas di Yogyakarta. Pertemuannya dengan seorang
anak gelandangan yang bernama Minul telah mengantarkannya dalam berbagai gejolak hidup. Keinginannya menyelamatkan Minul
didorong oleh rasa kasihan dan prihatin dengan nasib anak-anak kecil di
jalanan. Mereka harus mencuri untuk sekadar mengisi perut yang sudah beberapa
hari kosong. Berani mempertaruhkan nyawa demi menyambung hidup karena ketika
ketahuan mencuri, tak ada ampun bagi pelaku.
Fakultas Hukum sebuah universitas di Yogyakarta. Pertemuannya dengan seorang
anak gelandangan yang bernama Minul telah mengantarkannya dalam berbagai gejolak hidup. Keinginannya menyelamatkan Minul
didorong oleh rasa kasihan dan prihatin dengan nasib anak-anak kecil di
jalanan. Mereka harus mencuri untuk sekadar mengisi perut yang sudah beberapa
hari kosong. Berani mempertaruhkan nyawa demi menyambung hidup karena ketika
ketahuan mencuri, tak ada ampun bagi pelaku.
Gambaran kerasnya kota
Yogyakarta direntangkan dengan jelas oleh Imam. Bagaimana kehidupan anak
jalanan dibangun dengan menceritakan lika-liku kehidupan anak-anak jalanan. Selain
itu, yang menjadi menarik lagi dari novel ini adalah disinggungnya masa lalu
Suci yang hidup di Bandungan, Ambarawa. Sebuah tempat yang akrab sebagai kawasan prostitusi di kaki Gunung
Ungaran. Suci lahir dari sana, sebuah perkampungan yang selalu ingin dijauhi
oleh Suci. Dalam penggambarannya, jejak histori Bandungan menjadi kawasan
prostitusi ditarik untuk memberikan pandangan sejarah.
Yogyakarta direntangkan dengan jelas oleh Imam. Bagaimana kehidupan anak
jalanan dibangun dengan menceritakan lika-liku kehidupan anak-anak jalanan. Selain
itu, yang menjadi menarik lagi dari novel ini adalah disinggungnya masa lalu
Suci yang hidup di Bandungan, Ambarawa. Sebuah tempat yang akrab sebagai kawasan prostitusi di kaki Gunung
Ungaran. Suci lahir dari sana, sebuah perkampungan yang selalu ingin dijauhi
oleh Suci. Dalam penggambarannya, jejak histori Bandungan menjadi kawasan
prostitusi ditarik untuk memberikan pandangan sejarah.
Wilayah Bandungan dulu
digunakan oleh para tentara Belanda untuk melepas hasrat seksualnya dengan perempuan
pribumi. Tak sedar memakai, tentara Belanda juga menghargai jasa seksual dari
para perempuan di wilayah tersebut. Akhirnya, hal itu menarik banyak perempuan
untuk datang ke Bandungan, menjadi perempuan penjaja seks untuk tentara
Belanda. Kehadiran mereka tidak disalahkan oleh warga setempat. Tapi justru
didukung karena bisa menyelamatkan gadis-gadis asli Bandungan yang biasanya
diburu secara paksa oleh tentara Belanda. Jejak histori itu hingga kini masih
berlanjut.
digunakan oleh para tentara Belanda untuk melepas hasrat seksualnya dengan perempuan
pribumi. Tak sedar memakai, tentara Belanda juga menghargai jasa seksual dari
para perempuan di wilayah tersebut. Akhirnya, hal itu menarik banyak perempuan
untuk datang ke Bandungan, menjadi perempuan penjaja seks untuk tentara
Belanda. Kehadiran mereka tidak disalahkan oleh warga setempat. Tapi justru
didukung karena bisa menyelamatkan gadis-gadis asli Bandungan yang biasanya
diburu secara paksa oleh tentara Belanda. Jejak histori itu hingga kini masih
berlanjut.
Lika-liku dan alur cerita
yang tidak bisa ditebak memberikan efek penasaran bagi pembaca. Setelah
pertemuan dengan Sigit, seorang ketua teater Dharma di Yogyakarta, Suci
ditawari untuk memainkan lakon Drupadi dalam pentas Pandawa Dadu. Namun naas, saat sedang latihan di Pantai Parangtritis,
Sigit tewas akibat serangan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Suci akhirnya
harus menghadapi persoalan-persoalannya sendiri. Masalah cinta, kuliah, orang
tua, dan tentunya bertanggung jawab atas rasa ibanya kepada Minul.
yang tidak bisa ditebak memberikan efek penasaran bagi pembaca. Setelah
pertemuan dengan Sigit, seorang ketua teater Dharma di Yogyakarta, Suci
ditawari untuk memainkan lakon Drupadi dalam pentas Pandawa Dadu. Namun naas, saat sedang latihan di Pantai Parangtritis,
Sigit tewas akibat serangan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Suci akhirnya
harus menghadapi persoalan-persoalannya sendiri. Masalah cinta, kuliah, orang
tua, dan tentunya bertanggung jawab atas rasa ibanya kepada Minul.
Sayang, akhir cerita itu
menggantung. Dalam novel sebanyak 260 halaman ini menyisakan banyak pertanyaan.
Tentang siapa pembunuh Sigit yang menjadikan cerita ini semakin membuat pembaca
penasaran. Sampai di akhir, pertanyaan itu justru menggantung tanpa ada
jawaban.
menggantung. Dalam novel sebanyak 260 halaman ini menyisakan banyak pertanyaan.
Tentang siapa pembunuh Sigit yang menjadikan cerita ini semakin membuat pembaca
penasaran. Sampai di akhir, pertanyaan itu justru menggantung tanpa ada
jawaban.
Namun di luar kelemahan
itu, novel ini layak dibaca sebagai gambaran ikhwal perempuan yang sejati. Keberanian
Suci untuk membesarkan dan merawat anak jalanan inilah yang menjadi pemanggul
wacana besar terhadap isu perempuan di era sekarang.
itu, novel ini layak dibaca sebagai gambaran ikhwal perempuan yang sejati. Keberanian
Suci untuk membesarkan dan merawat anak jalanan inilah yang menjadi pemanggul
wacana besar terhadap isu perempuan di era sekarang.
Weiblich
Feminisme barat yang saat
ini bergelombang menjadi sasaran kritik novel ini. Kesetaraan perempuan diperjuangkan
untuk mengeksploitasi perempuan yang justru merendahkan. Gaya hidup
ditonjolkan, pemujaan atas kedudukan, kemewahan, kecantikan, dan keliaran
semakin didengungkan. Bahwa perempuan harus setara dengan laki-laki. Jika laki-laki
berhak untuk berpoligami, perempuan juga punya hak sama. Sedangkan keadaban,
kesantunan, dan kehormatan sebagai perempuan justru ditinggalkan.
ini bergelombang menjadi sasaran kritik novel ini. Kesetaraan perempuan diperjuangkan
untuk mengeksploitasi perempuan yang justru merendahkan. Gaya hidup
ditonjolkan, pemujaan atas kedudukan, kemewahan, kecantikan, dan keliaran
semakin didengungkan. Bahwa perempuan harus setara dengan laki-laki. Jika laki-laki
berhak untuk berpoligami, perempuan juga punya hak sama. Sedangkan keadaban,
kesantunan, dan kehormatan sebagai perempuan justru ditinggalkan.
Perempuan adalah makhluk
yang sudah digariskan setara dengan laki-laki. Hanya saja, peran dan
tanggungjawabnya berbeda sehingga perbedaan itu sebenarnya saling melengkapi. Perempuan
tidak harus menjadi laki-laki untuk setara. Perempuan cukup menjadi perempuan
saja. Margarete Mitscherlich dalam bukunya Die
Zukunft ist Weiblich (Masa depan adalah betina) secara jeli merumuskan dua
kutub, betina dan jantan, yang saling menyeimbangkan. Weiblich adalah istilah untuk perempuan, dan maennlich untuk laki-laki.
yang sudah digariskan setara dengan laki-laki. Hanya saja, peran dan
tanggungjawabnya berbeda sehingga perbedaan itu sebenarnya saling melengkapi. Perempuan
tidak harus menjadi laki-laki untuk setara. Perempuan cukup menjadi perempuan
saja. Margarete Mitscherlich dalam bukunya Die
Zukunft ist Weiblich (Masa depan adalah betina) secara jeli merumuskan dua
kutub, betina dan jantan, yang saling menyeimbangkan. Weiblich adalah istilah untuk perempuan, dan maennlich untuk laki-laki.
Weiblich
ditandai dengan sikap penuh tepa selira (tenggang rasa), toleran kepada pihak
lemah, bersikap merawat, dan memikirkan penderitaan orang lain. Berbeda dengan
pola pikir maennlich yang memuat hasrat
menguasai, nafsu agresif, serta memiliki perasaan yang paranoid. Implikasi sifat
maennlich ini mewujudkan dalam sikap
sulit mawas diri, curiga pada sesama, suka menyalahkan yang lain, tidak
mengakui kesalahan, dan penuh semangat balas dendam. Secara natural, betina
lahir untuk mengemong dan merawat dunia yang dekat dengannya.
ditandai dengan sikap penuh tepa selira (tenggang rasa), toleran kepada pihak
lemah, bersikap merawat, dan memikirkan penderitaan orang lain. Berbeda dengan
pola pikir maennlich yang memuat hasrat
menguasai, nafsu agresif, serta memiliki perasaan yang paranoid. Implikasi sifat
maennlich ini mewujudkan dalam sikap
sulit mawas diri, curiga pada sesama, suka menyalahkan yang lain, tidak
mengakui kesalahan, dan penuh semangat balas dendam. Secara natural, betina
lahir untuk mengemong dan merawat dunia yang dekat dengannya.
Kita bisa melihat sekarang
bagaimana perempuan justru bertransformasi meninggalkan Weiblich-nya dan mengangkat tinggi maennlich sebagai gantinya. Nama-nama seperti Angeline Sondakh,
Ratu Atut, Wa Ode Nurhayati, Artalyta Suryani, Nunun Nurbaeti tentu sudah tak
lagi asing di telinga kita. Sebuah status diri yang dibayar mahal untuk
mendapatkan pengakuan atas kekuasaan. Mereka dengan berani merampok milik
rakyat, tanpa kira dan minus rasa.
bagaimana perempuan justru bertransformasi meninggalkan Weiblich-nya dan mengangkat tinggi maennlich sebagai gantinya. Nama-nama seperti Angeline Sondakh,
Ratu Atut, Wa Ode Nurhayati, Artalyta Suryani, Nunun Nurbaeti tentu sudah tak
lagi asing di telinga kita. Sebuah status diri yang dibayar mahal untuk
mendapatkan pengakuan atas kekuasaan. Mereka dengan berani merampok milik
rakyat, tanpa kira dan minus rasa.
Ini berbeda dengan laku
yang ditunjukkan oleh Sonia Gandhi. Ia menolak jabatan sebagai perdana menteri
Indonesia, walau jabatan itu sebenarnya adalah haknya. Weiblich yang didemonstrasikan oleh Sonia Gandhi berhasil meredam
kericuhan bangsa dan negaranya. Ia dipuja sebagai ibu negara bagi rakyat India.
yang ditunjukkan oleh Sonia Gandhi. Ia menolak jabatan sebagai perdana menteri
Indonesia, walau jabatan itu sebenarnya adalah haknya. Weiblich yang didemonstrasikan oleh Sonia Gandhi berhasil meredam
kericuhan bangsa dan negaranya. Ia dipuja sebagai ibu negara bagi rakyat India.
Sekarang isu perempuan
bukan lagi bagaimana peran perempuan dapat merambah berbagai bidang. Tapi
bagaimana perempuan tetap bisa menjadi perempuan agar bisa memenuhi kodratnya
sebagai perempuan. Feminisme Barat yang kebablasan berpotensi membunuh weiblich. Sesuatu yang tidak patut
dibanggakan perempuan. Menjadi perempuan, cukup itu saja!
bukan lagi bagaimana peran perempuan dapat merambah berbagai bidang. Tapi
bagaimana perempuan tetap bisa menjadi perempuan agar bisa memenuhi kodratnya
sebagai perempuan. Feminisme Barat yang kebablasan berpotensi membunuh weiblich. Sesuatu yang tidak patut
dibanggakan perempuan. Menjadi perempuan, cukup itu saja!
M Irkham Abdussalam
Penikmat (cerita) perempuan

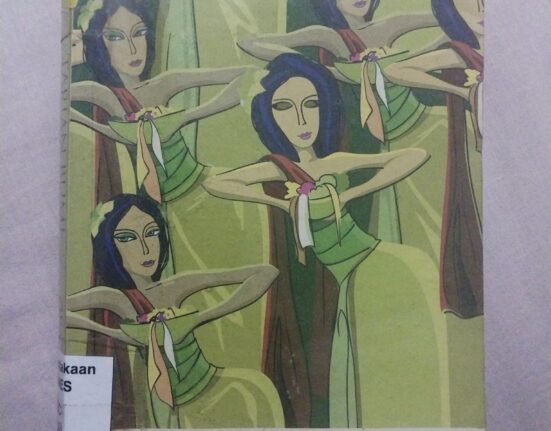
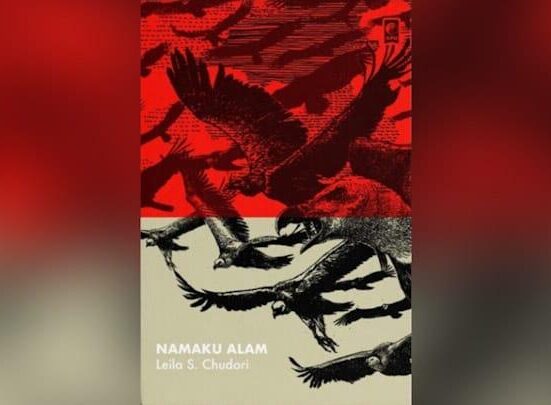
![Sampul novel Di Tanah Lada [Adhisti Kurnia]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251220-WA0140-551x431.jpg)
![Tampak buku "Bhumi" yang terletak di atas meja (BP2M) [Rabu, 10/12/2025]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2025/12/diskusi-upgris-sampul-551x431.jpg)