 |
| Seorang perempuan tengah berpose dalam swafoto (Dok. Mia) |
Menjelang peringatan Hari Buku Nasional yang jatuh tanggal 17
Mei, beberapa orang, komunitas, sampai institusi pendidikan berlomba-lomba merayakannya. Peringatan itu cukup sakral karena sampai saat ini gerakan
membaca buku dan berliterasi tengah digiat-giatkan. Apalagi, setelah
data World’s Most Literate Nations yang disusun oleh Central Conecticut State
University mempublikasikan posisi literasi Indonesia. Menurut data tersebut,
Indonesia berada di posisi 60 dari 61 negara yang diteliti. Posisi Indonesia
hanya unggul dari Bostwana dan berjarak tujuh tingkat dari negara tetangga
kita, Malaysia yang menduduki posisi 53. Ada pun negara dengan tingkat literasi
paling tinggi adalah Finlandia. Pemeringkatan yang diumumkan Maret lalu, adalah
studi deskriptif dengan menguji sejumlah aspek, termasuk variabel yang
dikelompokkan dalam lima kategori, yaitu perpustakaan, koran, input dan output sistem
pendidikan, serta ketersediaan komputer. (Tempo, 16 April 2016).
Mei, beberapa orang, komunitas, sampai institusi pendidikan berlomba-lomba merayakannya. Peringatan itu cukup sakral karena sampai saat ini gerakan
membaca buku dan berliterasi tengah digiat-giatkan. Apalagi, setelah
data World’s Most Literate Nations yang disusun oleh Central Conecticut State
University mempublikasikan posisi literasi Indonesia. Menurut data tersebut,
Indonesia berada di posisi 60 dari 61 negara yang diteliti. Posisi Indonesia
hanya unggul dari Bostwana dan berjarak tujuh tingkat dari negara tetangga
kita, Malaysia yang menduduki posisi 53. Ada pun negara dengan tingkat literasi
paling tinggi adalah Finlandia. Pemeringkatan yang diumumkan Maret lalu, adalah
studi deskriptif dengan menguji sejumlah aspek, termasuk variabel yang
dikelompokkan dalam lima kategori, yaitu perpustakaan, koran, input dan output sistem
pendidikan, serta ketersediaan komputer. (Tempo, 16 April 2016).
Jauh-jauh hari, Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan telah mencanangkan program
membaca selama 15 menit sebelum pelajaran di sekolah dimulai. Program ini
bertujuan untuk mendorong dan membiasakan peserta didik mengakrabi buku. Tidak
hanya itu, agar semakin keras gaungnya, Kemendikbud pun
mengangkat Najwa Shihab yang kadung populer sebagai perempuan cerdas dan
berwawasan sebagai Duta Baca Indonesia 2016-2021.
Kebudayaan telah mencanangkan program
membaca selama 15 menit sebelum pelajaran di sekolah dimulai. Program ini
bertujuan untuk mendorong dan membiasakan peserta didik mengakrabi buku. Tidak
hanya itu, agar semakin keras gaungnya, Kemendikbud pun
mengangkat Najwa Shihab yang kadung populer sebagai perempuan cerdas dan
berwawasan sebagai Duta Baca Indonesia 2016-2021.
Lantas, bagaimana dengan kampus yang menurut data panitia SNMPTN ini duduk diposisi 8 sebagai kampus yang paling
diminati? Unit Pelaksana Teknik (UPT) Perpustakaan Unnes mengadakan lomba foto
swafoto (selfie) dengan tema “Aku dan Perpustakaanku”. Hadiah yang ditawarkan
pun cukup menggiurkan, yakni tropi penghargaan, uang pembinaan ratusan ribu,
dan bingkisan dari Kepala UPT.
diminati? Unit Pelaksana Teknik (UPT) Perpustakaan Unnes mengadakan lomba foto
swafoto (selfie) dengan tema “Aku dan Perpustakaanku”. Hadiah yang ditawarkan
pun cukup menggiurkan, yakni tropi penghargaan, uang pembinaan ratusan ribu,
dan bingkisan dari Kepala UPT.
Syarat dan ketentuan lomba pun sangat mudah. Tinggal foto di
perpustakaan Unnes, unggah di Instagram, beri caption menarik, dan jangan lupa hashtag #HariBukuNasional #UptPerpustakaanUnnes. Sudah begitu, jika
ingin menjadi pemenang cukup memperhatikan objek, kualitas foto dan
banyaknya likes.
perpustakaan Unnes, unggah di Instagram, beri caption menarik, dan jangan lupa hashtag #HariBukuNasional #UptPerpustakaanUnnes. Sudah begitu, jika
ingin menjadi pemenang cukup memperhatikan objek, kualitas foto dan
banyaknya likes.
Lomba ini jelas jauh dari pemaknaan Hari Buku Nasional.
Logika antara lomba dan peringatan Hari Buku Nasional tidak sinkron. Apa
korelasi antara buku dan budaya literasi dengan
kegiatan swafoto yang butuh waktu tak sampai 2 detik. Ajang ini menunjukkan
bahwa pengurus perpustakaan sekadar memanfaatkan ekstasi massa yang gandrung
pada budaya swafoto. Kita patut menduga, budaya swafoto lebih rajin dilakukan
daripada membaca buku dan berliterasi. Maka, ajang ini tak lebih dari sekadar pengekalan budaya swafoto, daripada membumikan budaya literasi.
Logika antara lomba dan peringatan Hari Buku Nasional tidak sinkron. Apa
korelasi antara buku dan budaya literasi dengan
kegiatan swafoto yang butuh waktu tak sampai 2 detik. Ajang ini menunjukkan
bahwa pengurus perpustakaan sekadar memanfaatkan ekstasi massa yang gandrung
pada budaya swafoto. Kita patut menduga, budaya swafoto lebih rajin dilakukan
daripada membaca buku dan berliterasi. Maka, ajang ini tak lebih dari sekadar pengekalan budaya swafoto, daripada membumikan budaya literasi.
Kuasa Foto
Saya tak bisa memastikan, apa maksud dan tujuan panitia perpustakaan membuat lomba swafoto ini. Tapi jelas, lomba swafoto ini mengalami cacat logika jika diadakan untuk
memperingati Hari Buku Nasional.
memperingati Hari Buku Nasional.
Menukil tesis Jean Baudrillard, foto adalah sebuah kebohongan.
Hari ini, kita hidup di dalam dunia yang oleh Baudrillard disebut hyper-reality atau hiperrealita atau realitas semu. Era di mana batas antara realitas dan citra
telah melebur. Bahkan, citra telah berubah menjadi realitas itu sendiri.
Hari ini, kita hidup di dalam dunia yang oleh Baudrillard disebut hyper-reality atau hiperrealita atau realitas semu. Era di mana batas antara realitas dan citra
telah melebur. Bahkan, citra telah berubah menjadi realitas itu sendiri.
Hiperrealita sebagai anak dari postmodernisme menekankan
emosi ketimbang rasio, media ketimbang isi, tanda ketimbang makna, kemajemukan
ketimbang penunggalan, kemungkinan ketimbang kepastian, permainan ketimbang
keseriusan, keterbukaan ketimbang pemusatan, yang lokal ketimbang yang
universal, fiksi ketimbang fakta, estetika ketimbang etika, dan narasi
ketimbang teori (Ariel Heryanto, 1994: 80).
emosi ketimbang rasio, media ketimbang isi, tanda ketimbang makna, kemajemukan
ketimbang penunggalan, kemungkinan ketimbang kepastian, permainan ketimbang
keseriusan, keterbukaan ketimbang pemusatan, yang lokal ketimbang yang
universal, fiksi ketimbang fakta, estetika ketimbang etika, dan narasi
ketimbang teori (Ariel Heryanto, 1994: 80).
Maka yang dicapai oleh lomba swafoto itu sebatas tanda
daripada makna, permainan ketimbang keseriusan, estetika ketimbang etika, dan
narasi ketimbang teori. Dalam foto, orang bisa
seolah-olah membaca buku, tapi apakah benar-benar ia membaca buku secara
tuntas, hal itu sangat bisa digugat. Dalam foto, orang bisa tampak
berliterasi, namun apakah benar-benar berliterasi, hal itu butuh diuji. Di sini, tesis Baudrillard tentang
kebohongan foto menemukan faktanya.
daripada makna, permainan ketimbang keseriusan, estetika ketimbang etika, dan
narasi ketimbang teori. Dalam foto, orang bisa
seolah-olah membaca buku, tapi apakah benar-benar ia membaca buku secara
tuntas, hal itu sangat bisa digugat. Dalam foto, orang bisa tampak
berliterasi, namun apakah benar-benar berliterasi, hal itu butuh diuji. Di sini, tesis Baudrillard tentang
kebohongan foto menemukan faktanya.
Esai yang ditulis Udji Kayang berjudul Tanpa
Foto, Mereka Bisa Apa? yang dimuat di Harian Solopos (5 April 2016) merekam bukti bahwa foto adalah sebuah
kebohongan. Udji menuliskan, “Maret lalu, aku mengunjungi Pameran Made in Commons yang diselenggarakan
Kunci dan kawan-kawan komunitas di Jogja. Di salah satu ruangan, beberapa karya
tipografi dipajang. Tipografi yang persis kujumpai kali pertama bertuliskan
“Mulai dari situ, gw belajar menipu
dari foto, hahahahahahahaha.” Agan
Harahap, pencetus kalimat itu sekaligus pegiat desain grafis, praktis
mengiyakan kebohongan foto.”
Foto, Mereka Bisa Apa? yang dimuat di Harian Solopos (5 April 2016) merekam bukti bahwa foto adalah sebuah
kebohongan. Udji menuliskan, “Maret lalu, aku mengunjungi Pameran Made in Commons yang diselenggarakan
Kunci dan kawan-kawan komunitas di Jogja. Di salah satu ruangan, beberapa karya
tipografi dipajang. Tipografi yang persis kujumpai kali pertama bertuliskan
“Mulai dari situ, gw belajar menipu
dari foto, hahahahahahahaha.” Agan
Harahap, pencetus kalimat itu sekaligus pegiat desain grafis, praktis
mengiyakan kebohongan foto.”
Alhasil, lomba ini sekadar ujuk kebolehan pamer diri, dengan
latar perpustakaan. Literasi sebagai gaung yang harus diperjuangkan tak jadi
prioritas utama karena pikiran terlalu sibuk mencari angle yang tepat, mengedit foto agar tampak mewah, dan menyebarkannya
ke berbagai dinding media sosial. Ujungnya, buku tak terbaca. Dorongan untuk menggiatkan diri dalam budaya sinau tak
tersentuh. Yang ada, histeria sesaat berfoto bersama buku-buku. Sambil
membayangkan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000 untuk juara satu.
latar perpustakaan. Literasi sebagai gaung yang harus diperjuangkan tak jadi
prioritas utama karena pikiran terlalu sibuk mencari angle yang tepat, mengedit foto agar tampak mewah, dan menyebarkannya
ke berbagai dinding media sosial. Ujungnya, buku tak terbaca. Dorongan untuk menggiatkan diri dalam budaya sinau tak
tersentuh. Yang ada, histeria sesaat berfoto bersama buku-buku. Sambil
membayangkan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000 untuk juara satu.
Perlu dipahami, meski di dalam penelitian di atas mencantumkan indikator akses masyarakat atas perpustakaan,
bukan berarti aktivitas itu sekadar datang dan
berfoto di perpustakaan. Indikator itu merujuk pada penjelasan bahwa masyarakat
yang berliterasi adalah yang membaca setamat-tamatnya dan sebanyak-banyaknya
buku di perpustakaan. Apakah hal itu (akan) terjadi dalam lomba
ini? Saya meragu!
bukan berarti aktivitas itu sekadar datang dan
berfoto di perpustakaan. Indikator itu merujuk pada penjelasan bahwa masyarakat
yang berliterasi adalah yang membaca setamat-tamatnya dan sebanyak-banyaknya
buku di perpustakaan. Apakah hal itu (akan) terjadi dalam lomba
ini? Saya meragu!
Jika boleh usul, untuk memperingati Hari Buku Nasional, pihak
UPT Perpustakaan Unnes bisa mengadakan lomba resensi buku atau menulis esai. Setidaknya,
dalam lomba itu, peserta yang ikut harus membaca buku. Dalam menulis, kita
perlu referensi, dan di mana pusat referensi itu berada? Tentu perpustakaan
menempati urutan pertama sebagai ruang penyedia referensi. Setidaknya
kerja literasi terlihat dalam aktivitas lomba yang saya tawarkan. Daripada sekadar berkunjung ke perpustakaan dan mengambil
foto yang hanya butuh waktu dua detik saja. Selanjutnya pulang, menunggah foto, dan menyebarkannya. Sudah begitu, hadiahnya lebih besar
daripada honor menulis di koran lokal. Padahal hanya sekadar swafoto. Tak perlu membaca buku, apalagi mengkliping
tulisan dan berita.
UPT Perpustakaan Unnes bisa mengadakan lomba resensi buku atau menulis esai. Setidaknya,
dalam lomba itu, peserta yang ikut harus membaca buku. Dalam menulis, kita
perlu referensi, dan di mana pusat referensi itu berada? Tentu perpustakaan
menempati urutan pertama sebagai ruang penyedia referensi. Setidaknya
kerja literasi terlihat dalam aktivitas lomba yang saya tawarkan. Daripada sekadar berkunjung ke perpustakaan dan mengambil
foto yang hanya butuh waktu dua detik saja. Selanjutnya pulang, menunggah foto, dan menyebarkannya. Sudah begitu, hadiahnya lebih besar
daripada honor menulis di koran lokal. Padahal hanya sekadar swafoto. Tak perlu membaca buku, apalagi mengkliping
tulisan dan berita.
Namun, ini sekadar usul saja. Saya paham, kita hidup dalam
kultur yang sangat sensitif terhadap kritik. Kritik dituntut
menyertakan solusi. Budaya belajar dan menerima kritik dengan kepala terbuka nyaris tak ada. Kritik
yang tajam diperlakukan tidak dewasa oleh pihak yang mengaku telah dewasa.
kultur yang sangat sensitif terhadap kritik. Kritik dituntut
menyertakan solusi. Budaya belajar dan menerima kritik dengan kepala terbuka nyaris tak ada. Kritik
yang tajam diperlakukan tidak dewasa oleh pihak yang mengaku telah dewasa.
Budaya kritik yang harus menyertakan solusi jauh-jauh hari telah disampaikan orang nomor satu di Unnes ini. Jadi, jangan anggap saya kurang ajar karena telah menyodorkan solusi kepada pihak yang lebih pintar
dan berkedudukan tinggi. Meski sesungguhnya, hal itu sangat aneh.
dan berkedudukan tinggi. Meski sesungguhnya, hal itu sangat aneh.
M. Irkham Abdussalam
Fotografer Tabloid NuansA


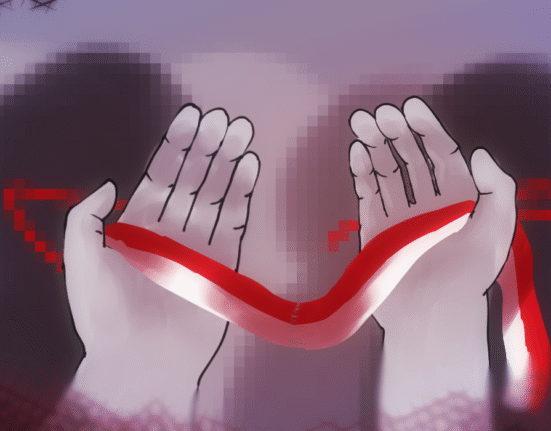

![ilustrasi opini "Informatika: Menyingkap Potensi Pikiran dan Perasaan Manusia" [BP2M/Alya Aisyah]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2025/01/1-551x431.png)
![Ilustrasi "Perempuan Di Ambang Pilihan" [BP2M/Alya]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2024/12/Ilustrasi-perempuan-551x431.png)
![Ilustrasi Opini "Korupsi, Kelompok Aksi, dan Peran Pers" [BP2M/Hanna]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2024/12/ilustrasi-korupsi_20241206151553-551x431.png)
3 Comments
Comments are closed.