Oleh : Mukhammad Najmul Ula
[Tulisan ini bukan disusun oleh penyelenggara, pelaku, atau apalah namanya, yang secara langsung terlibat dalam proses elektoral di tingkat mahasiswa. Jadi, wajar jika ada bias subyektif dan pengkritik dipersilakan menghujat di lini masa media sosial penulis]
Sebetulnya sangat memalukan bila si Fulan, seorang mahasiswa yang mengaku lebih tahu politik daripada siapa pun di kampus ini, ternyata memiliki ketidakpekaan pada bidang yang digelutinya di tingkat kampus. Pengetahuannya tentang politik makro, hubungan internasional, atau politik praktis di tingkat nasional berbanding terbalik dengan ketumpulannya dalam mencerna siapa di antara kawannya yang memiliki ambisi berkuasa di lembaga kemahasiswaan.
Si Fulan bersama segerombol karibnya dan sejuta mahasiswa lainnya, ialah contoh besar “penderita” buta politik versi Bartolt Brecht. Sabda Brecht yang termasyhur itu menjadi motivator terbesar bagi pembelajar politik praktis, tetapi tidak salah apabila masih ada saja manusia dungu yang terbenam dalam ketidakpeduliannya. Wally with the brolly, orang bodoh dengan payung keabaiannya—sori, Steve McLaren.
Sayangnya, penulis ialah manifestasi nyata gambaran orang bodoh di atas: tolol, pemalas, bukan panutan, tak punya massa, dan tak tahu caranya berpolitik praktis. Menjelang pemilihan raya tahun ini, mahasiswa-kurang-pergaulan (semacam saya) kembali diantar menuju persaingan antar elite yang kita bahkan tak tahu latar belakang mereka. Pilihan hidup untuk berjauh-jauh dari dunia itu menimbulkan konsekuensi logis: dieksploitasi secara individu, dimanfaatkan secara kelompok, digiring secara kolektif, dan di-framing bila tak cerdas.
Bukan apa-apa, memangnya pengumpulan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) bagi para kandidat itu siapa yang memperoleh keuntungan? Puluhan mahasiswa yang KTM dan nomor teleponnya dikumpulkan, bukan tidak mungkin hanya akan menjadi penonton dan tidak pernah memperoleh sentuhan dari “pihak” terpilih.
Lantas, Pemira sebagai perwujudan demokrasi di student government, sudahkah mengoreksi adagium “dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa”?
Suatu waktu senior kanca ngopi berwasiat, “Jangan sampai keikutsertaanmu dalam organisasi kampus malah menjadikanmu sapi perah. Kau yang bekerja keras, atasanmu berasyik masyuk menikmati ketenaran.”
Senior yang kementhus itu mencontohkan beberapa program kerja lembaga kemahasiswaan yang seolah-olah digarap sebagai “inovasi generasi muda”, padahal ditujukan untuk mendongkrak nama si pemimpin besar dalam konstelasi politik kampus. Meskipun, Ia juga pernah memerah jiwa dan raga penulis, pendapat demikian tidak boleh dihiraukan begitu saja, terlebih bagi para pengkaji politik dalam aras akademik. Ada tindakan di balik tindakan; ada udang di balik batu; terdapat makna di balik makna; there is something bigger beyond the wall.
Pada kesempatan lain, sahabat-merangkap-musuh pernah memantik pikiran penulis ketika bertanya apa sebenarnya penggerak mahasiswa penuh ambisi seperti mereka mengincar posisi di pemerintahan mahasiswa, lalu kenapa organisasi non-kampus tertarik bertungkus lumus di dalamnya?
Pertanyaan pertama menjadi suatu kewajiban bagi segala jenis organisasi kampus untuk mencantumkannya di formulir pendaftaran. Meskipun, kebanyakan (calon) organisatoris menjawab klise—semacam “ingin membunuh waktu”, “mencari pengalaman baru”, “berburu relasi”, dan sejenisnya-.
Secara garis besar Para-Pencari-Kuasa itu dapat kita khayal sedang menjawab begini, “Saya tahu perjuangan di dunia nyata selepas jadi mahasiswa itu sekejam Sylla dan Charybdis memangsa para pelaut. Bila saya hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu, saya tidak punya daya tawar sama sekali di dunia luar. Keterlibatan saya di lembaga kemahasiswaan antara lain untuk mendapatkan posisi sepenting mungkin di sini, agar ketika saya lulus nanti mempunyai curriculum vitae memadai. Saya juga sudah berburu peran juga di organisasi ekstra kampus. Jadi, mudah-mudahan saya bisa meraih ‘sesuatu yang besar’ melalui jalan ini.”
Pertanyaan kedua merupakan persoalan sensitif dan telah diimplementasikan berpuluh-puluh tahun lamanya di kampus-kampus seluruh Indonesia. Misi mereka untuk turut berjibaku di kawah candradimuka bisa diduga merupakan cara untuk menjaring kader berkualitas baru.
Lebih jauh dari itu, beberapa “institusi” diketahui menyemai bibit, menanam, dan merawatnya dengan mekanisme terstruktur yang melibatkan lembaga-lembaga “resmi” kampus tertentu, yang tentu saja membutuhkan modal finansial bagi “institusi” itu sendiri. Dengan meletakkan sejumlah “kader terbaik”-nya di ring satu student government, benefit popularitas yang diikuti keuntungan lain bisa didapat.
Organisasi ekstra dengan lihai membina putera didiknya agar tercetak seperti yang mereka ingin, lengkap dengan doktrinasi yang akan dilanjutkan putera-putera didik itu pada masanya nanti. Ayam itu bereproduksi, bertelur, mengerami, menetaskan, dan membesarkan piyik-piyiknya sendiri.
Hanya saja, dengan masih relevannya istilah mahasiswa kupu-kupu, yang artinya masih terdapat mahasiswa kurang pergaulan dan buta politik kampus. Fenomena adu hantam politisi mahasiswa di atas hanya menjadi pergulatan dalam lingkaran semata.
Si mahasiswa polos tidak akan pernah tahu KTM yang ia kumpulkan dipergunakan bakal-calon-kandidat pengincar kursi untuk mengincar jabatan yang sebenarnya pesanan dari luar.
Mahasiswa baru, yang oleh para kakak tingkat kuker sering diincar untuk digebet, nampaknya masih menjadi segmen terbesar untuk menjaring suara.
KTM si mahasiswa baru (maba) akan dihimpun, diverifikasi oleh komisi pemilihan, lalu dikembalikan ke pemiliknya. Kandidat terpilih belum tentu akan membalas budi si maba budiman, kecuali mengadakan serangkaian program kerja (progja) hedonis selama masa kepemimpinannya.
Pergulatan menuju pemira hanya diperjuangkan oleh mereka yang teramat rajin. Berkeliling kos mengajak tiap orang memilih kandidatnya, lalu ia akan beroleh “imbalan” atas jasanya itu. Ia pula yang akan menikmati hasil kerja kerasnya di kampus: pekerjaan layak di masa mendatang.
Jadi, mahasiswa kupu-kupu adalah massa mengambang; konstituen yang dilupakan; publik yang dicap bodoh. Kalau menurut whatsapp status kolega, bunyinya begini, “Berburu KTM lalu lupa konstituen.”
Lintang Pratama, 27 November 2017



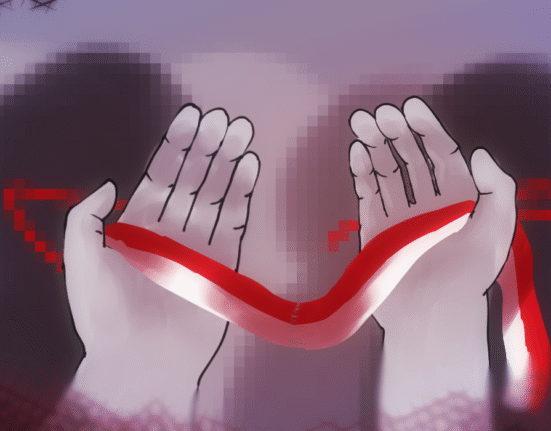

![ilustrasi opini "Informatika: Menyingkap Potensi Pikiran dan Perasaan Manusia" [BP2M/Alya Aisyah]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2025/01/1-551x431.png)
![Ilustrasi "Perempuan Di Ambang Pilihan" [BP2M/Alya]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2024/12/Ilustrasi-perempuan-551x431.png)
![Ilustrasi Opini "Korupsi, Kelompok Aksi, dan Peran Pers" [BP2M/Hanna]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2024/12/ilustrasi-korupsi_20241206151553-551x431.png)