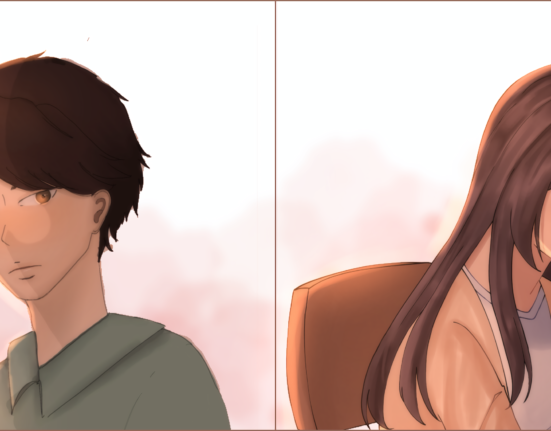|
| Senja (BP2M Irkham) |
DI sebuah senja, Nila
duduk di beranda bersama nenek. Menatap ke barat kepada matahari sore.
Mengerling kemudian tertawa kepada sinar surya. Cahaya itu membalasnya dengan
sentuhan hangat yang menerpa keemasan di setengah tubuhnya. Rambut hitamnya
terlihat kemerahan. Lagi, ia melihat ke langit sambil menggigit-gigiti
punggung jari telunjuknya yang telah basah oleh air liurnya. Sampai-sampai
membengkak dan mati rasa. Tangan kiri-nya memukul-mukul nampan tua yang telah
berkarat. Tak ada teman sebayanya yang pernah bermain bersamanya. Nampan dan
kesepianlah temannya. Ia menyanyikan sebuah kumandang dengan bahasa yang aneh.
Tak satu pun orang bisa memaknainya. Lantunan yang syairnya tak pernah bisa ia
jelaskan pada orang lain bahwa itu suara hatinya.
Apalagi Ipah tahu bahwa Nila mengalami gangguan pada syaraf otaknya.
Perkembangan mental Nila berjalan tak normal. Ipah malu pada orang-orang di
sekitarnya. Ipah cemas dicap yang macam-macam. Ipah menjadi risih pada buah
hatinya sendiri. Sejak saat itu nenek yang merawatnya. Janda tua yang kesepian
itu telah menemukan seseorang yang me-nemaninya di usia uzur.
Tak jelas ia maksudkan apa.
penanda bahwa saatnya ia akan mengisi perutnya. Ia tahu tak ada seorang pun
kecuali dirinya di rumah itu. Ia berjalan tertatih menuju dapur. Menyeret
langkah kakinya yang pengkor. Punggung telunjuknya kembali menjadi korban rasa
laparnya. Ia gigiti hingga nampak menghitamkebiruan lebam.
langkah kakinya menuju belakang rumah. Tak ia temui juga apa-apa. Hanya segelas
air teh basi tergeletak menganga. Menarik perhatian lalat mengitarinya. Satu,
dua, tiga teguk ia rengkuh minuman yang telah berasa agak aneh itu. Terkucur
deras melewati kerongkongannya yang kering.
kembali mendapatkan kesempatannya bermanja dengan nenek. Saat senja pula Nila
menumpahkan kesahnya dalam pelukan nenek. Setelah malam agak matang Nenek akan
mengajaknya istirahat di kamar yang sempit dan berwajah remang. Dua manusia
itu berbaring bersama. Berebutan menghembuskan nafas. Nenek merapikan kaki
Nila. Nenek tak akan berhenti menepuk-nepuk pahanya dengan lembut hingga ia
lemah dalam tidurnya. Sesekali Nila mengigau memanggil-manggil seseorang.
Bukan nama Ipah, ibunya. Tapi nenek.
ada lawan bicara. Memandangi langit di tengah terik. Memukul-mukul nampan yang
suaranya akan mengusik telinga. Bernyayi dengan bahasa yang tak bisa
dimengerti. Ia memandang sekelilingnya deng-an perhatian yang sederhana. Tak
pernah ada ruang dendam dalam hatinya ketika orang-orang yang memandangnya akan
menumpuk rasa jijik.
dari keningnya. Nafasnya berhembus panjang pendek tak berirama. Ini malam
ketiga ia terbangun di tengah malam.
Perkataan Nenek untuk menakut-nakutinya supaya kembali berbaring tidur.
atap yang terlindung gelap.
masih mengingat-ingat sesuatu yang dilihatnya di mimpi tadi.
tak sempurna.
terpaksa diikat, mengikuti gerak tubuhnya berjalan beberapa langkah dalam
gelap. Menuang segelas air putih. Dengan penglihatan yang telah agak redup air
itu dijulurkan pada cucunya. Nila meraihnya dengan tangan kiri. Tangan kanannya
tak berfungsi wajar sebagaimana kiri sejak lahir. Hanya bisa mengepal dan melambai-lambai.
Setelah menenggak segelas air putih Nila seolah telah melepas sesuatu yang
membebani pikirannya. Ia lega.
terjingkat dari tidur. Didekapnya lengan nenek erat-erat. Seakan tak rela jika
nenek beranjak dari sampingnya. Ia menangis tanpa sebab. Wanita tua itu
membujuk Nila agar berhenti menangis. Menawarinya air putih seperti biasa jika
ia terbangun. Tapi Nila tak mau kalau nenek bangun dan lepas dari tangannya.
Seolah ia tak ingin nenek pergi darinya.
merayap di awang-awang. Sama halnya dengan kebiasaannya yang telah lalu ketika
nenek masih ada di sampingnya. Sekarang Nila sendiri. Nenek meninggalkannya.
Nenek pergi ke tempat yang jauh sekali. Ia akan menjemput Nila. Begitu kata
nenek suatu kali dalam mimpinya. Tak ada lagi yang menepuk-nepuk paha Nila
jika ia susah tidur. Tak ada pula yang menyuguhinya air putih saat ia terbangun
di tengah malam buta. Tak ada lengan nenek yang bisa ia peluk saat ia
ketakutan pada malam.
nampan usangnya. Tak lagi menyanyi dengan bahasanya. Namun, nyanyiannya bernada
bisu. Anginlah yang memainkan irama hatinya. Nila mendengarnya bagai simfoni
yang terurai menjelang malam. Rupa jalan tersengat sepi. Tatapan Nila kosong
pada sebuah gang kecil yang biasa dilalui nenek. Tak seorang datang
menemuinya. Nila menanti nenek datang menjemputnya. Ia selalu menanti nenek.
karena benar-benar ia me-nerimanya, atau entah mungkin karena ia khawatir
gunjingan te-tangga yang mengolok-oloknya sebagai ibu yang tak bertanggung
jawab.
mewakili hal-hal yang ia benci, hal-hal yang membuat dirinya bersedih dan
takut. Nila menempatkan Ipah dalam ruang hitamnya. Baginya Ipah selalu membawa
kesedihan. Ipah tidak senang jika Nila menabuh nampan kesayangannya. Tak suka
jika Nila memandang surya kesukaannya. Tak senang kala Nila menunggui rumah
nenek. Menyuruhnya tidur di tikar sendirian. Tak boleh menyanyi-nyanyi. Mencubitinya
tanpa alasan yang jelas hingga kulitnya penuh bekas-bekas biru. Ketakutan Nila
begitu pekatnya pada Ipah.
Ia lewatkan aromanya yang khas. Cahaya keemasan yang unik telah pudar berganti
warna nila. Keadaan telah benar-benar sepi. Bukan sepi yang tiap hari menemani
Nila. Tapi sepi yang lain yang ada. Sepi yang sesungguhnya sepi. Bangku di
teras rumah nenek sudah tak ada sesosok anak yang menenteng nampan. Di senja
itu juga sudah tak ada lagi suara nyaring Nila. Rumah itu kosong menatap sepi.
Rumah itu seaakan tak punya daya. Kokohnya hilang. Gang yang biasa dilewati
nenek berganti angin yang hembusannya menyeruak memenuhi sepanjang ia berlalu.
Nila telah berlalu dari rumah itu. Berlalu dari kehidupan Ipah. Nila tak sabar
menunggu sebuah janji yang pernah hadir dalam mimpinya.
Jepara, April 2010
Oleh Wahyu Ameer, lahir di Jepara 24 Juni 1989. Masih kuliah di Universitas
Negeri Semarang, Prodi Sastra Indonesia. Aktif di Komunitas Kalimasada
Semarang.

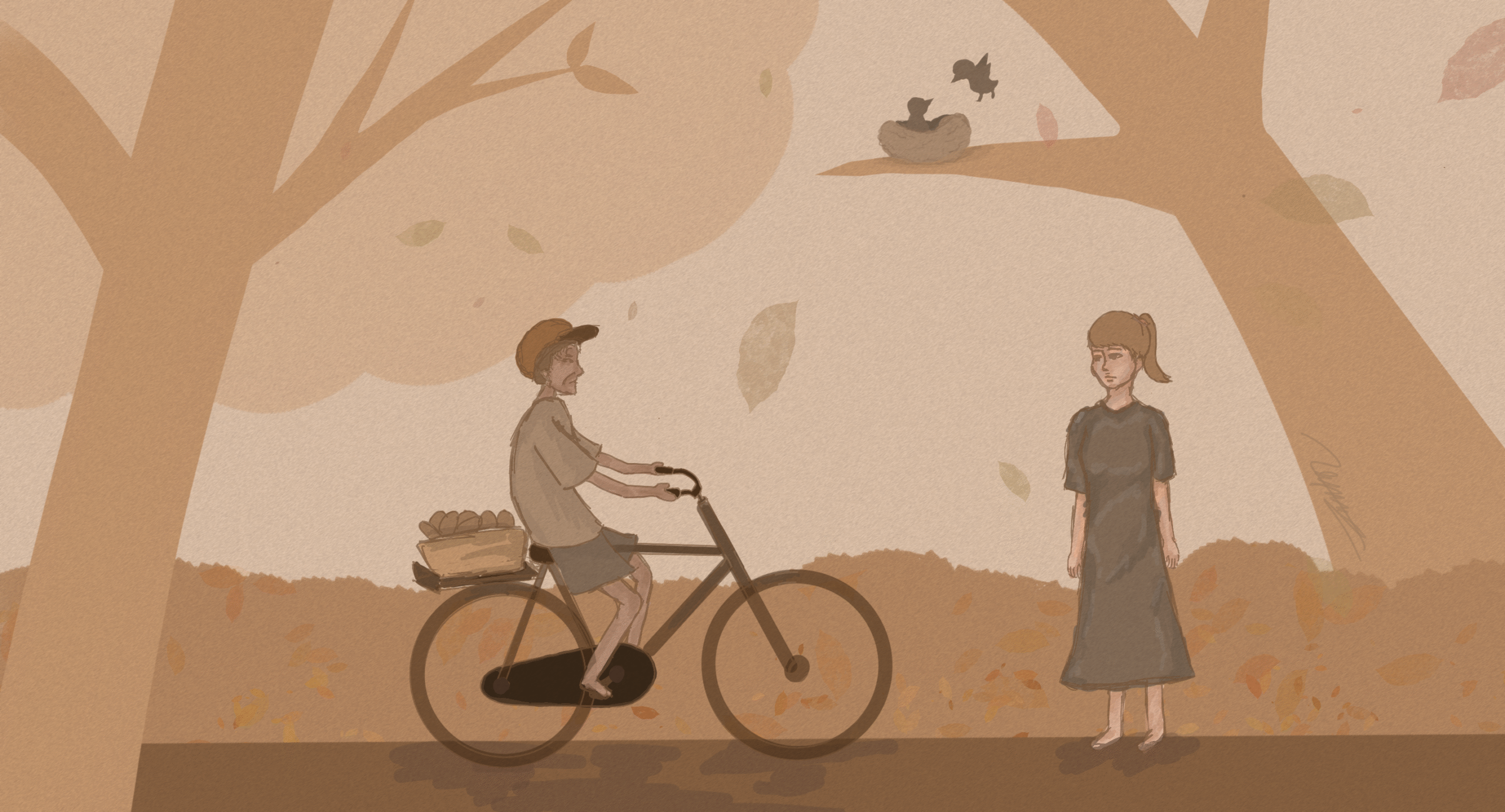
![Ilustrasi Puisi “Lembar Koda Sang Pecundang” [BP2M/Hanna Watsiqatul Fadha'il]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2025/03/1-551x431.png)