Siapa yang menyangka, ketika rezim otoriter telah runtuh, pers mahasiswa (persma) juga kehilangan musuh. Tidak ada lagi kesatuan isu yang bisa diperjuangkan bersama sebagai sesama pegiat persma. Pemberitaan yang tajam, kritis dan independen telah dianggap a historik. Sementara menyelenggarakan penerbitan sebagai bagian dari pendidikan publik – khususnya mahasiswa – untuk bersikap rasional dan melakukan penerbitan sebagai proses pengkaderan profesional adalah tugas berat yang musti diemban.
Gejala kapitalisme yang melanda pers umum makin menjadikan etos kerja wartawan dan harapan publik terhadap peran perubahan sosial makin menipis. Pers umum makin terjebak dengan pola pemberitaan talking news (jurnalisme kata-kata) yang kering fakta dan empiris. Jurnalisme preman dan media pornografis mulai mencemari pers umum. Disaat ruh gerakan pers mahasiswa sebagai kontrol sosial melalui bentuk pemberitaan yang tajam, kritis dan independen yang selama ini dianggap sebagai a-historik belaka telah berangsur membaik. Pengekangan dan tantangan datang dari berbagai pihak. Parahnya itu juga datang dari internal pers mahasiswa sendiri.
Sebagai motor penggerak reformasi, kalangan kampus ternyata belum bisa menjamin kebebasan persma yang juga bagian dari kebebasan berekspresi. Masih terdapat sejumlah kasus pengekangan kebebasan berekpresi dilingkungan persma. Diawali dengan pelanggaran terbit Solidaritas (Persma Unas), pembreidelan Arena (IAIN Sunan Kalijaga), Opini (Fisip Undip), Dialogue (Fisip Unair), Vokal (Ikip PGRI) dan yang baru beberapa minggu yang lalu majalah Lentera (UKSW) dibreidel oleh pihak kampus dan kepolisian. Pembreidelan adalah cara kuno dan orde baru yang semestinya sudah ditinggalkan di era sekarang.
Sungguh, ketika tulisan ini dipublikasikan, saya ingin bertanya kepada pimpinan kampus terkait masalah Lentera. Para pengelola Lentera adalah anak-anak muda yang rata-rata lahir di tahun-tahun menjelang keruntuhan Soeharto, bisa jadi yakin bahwa mereka tidak akan mengalami sesuatu yang buruk saat menulis laporan utama tentang tragedi 1965. Tetapi faktanya versi cetak majalah tersebut harus ditarik dari peredaran, hanya karena dianggap meresahkan beberapa pihak. Ditambah lagi, para pengelola majalah tersebut harus berurusan dengan pihak kepolisian.
Breidel adalah istilah dari bahasa Belanda yang berarti pemberangusan, pelarangan, atau pembatasan terhadap media massa atau produk pers. Breidel terjadi sejak masa hindia belanda dan gencar-gencarnya pada masa Orde Baru. Dengan posisi perlindungan yang lemah, persma rawan dibreidel. Persma secara struktur dilindungi oleh pimpinan kampus. Sayangnya, itu malah menjadi persoalan sejak dulu hingga sekarang. Ketergantungan kepada pihak pimpinan kampus yang terkadang menjadi objek kritik pemberitaan kerap melahirkan problematika tersendiri. Pembreidelan, penghentian dana cetak, dan kewajiban yang mengharuskan terbitan masuk meja birokrasi sebelum cetak adalah cara-cara klasik yang dipakai pemimpin kampus. Akibatnya, independensi dan ketajaman berita tidak ada, bahkan cenderung melahirkan berita yang dekat dengan humas kampus.
Persma sendiri juga tidak bisa dibilang kuat dan mapan secara manajemen. sebab personil persma hanya dikendalikan oleh komitmen. Adanya kesamaan minat dan bakat menjadi pengikat utama. Persma, dari kandungan nama memang sudah berat dan mulia. Pers dan mahasiswa mengandung arti spirit intelektualitas, keperpihakan pada moral, etika dan rakyat bawah ditambah pers mahasiswa juga harus independen. Seolah persma berat di namanya, maka personil persma biasanya juga tidak banyak. Tidak semua mahasiswa mampu mengemban tugas seberat itu.
Krisis Kepercayaan
Persma paska reformasi 1998, tampak ada gejala krisis kepercayaan diri yang amat parah. Persma yang tidak sepopulis organisasi lainya: menggerakan mahasiswa ke jalan sambil mengibarkan bendera dan atribut organisasi. Akibatnya pengkaderan dalam tubuh pers mahasiswa menjadi tidak mulus dan gampang dilakukan. Sistem kaderisasi, kultur internal, umur kemapanan dan sokongan para alumni mutlak menjadi faktor yang tidak terpisahkan.
Krisis ketidakpercayaan: ketidakpercayaan diri sebagai agen perubahan, ketidakpercayaan diri dalam memainkan peranan stategis dalam konstelasi demokrasi menjadikan pers mahasiswa hadir di komunitasnya hanya sekadar memenuhi jadwal penerbitan yang dibuat menurut logika sebuah unit kegiatan mahasiwa. Persis apa yang ditulis Masduki (2003), yang pernah menjabat sebagai ketua aliansi jurnalis independen (AJI) Yogyakarta, produk terbitan persma muncul bukan atas dasar kesadaran penuh atau kebutuhan menyalurkan idealisme tetapi tuntutan rutinitas agar legitimasi sebagai bagian dari kegiatan mahasiswa tetap terjaga. Lebih celaka lagi, pers mahasiswa tinggal papan nama, mati suri tanpa kepastian terbit. Jarak antara orientasi penyaluran hobi menulis dengan penyaluran idealisme makin tipis sehingga muatan isi persma makin mirip buletin birokrasi kampus.
Krisis kepercayaan dalam tubuh persma sebenarnya bukan tanpa solusi, meskipun bukan perkara mudah dan dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Persma perlu membangun komunitas pers yang memiliki kesamaan minat dan bakat menulis, kegemaran berorganisasi dan berkumpul. Kepekaan sosial mutlak perlu terus dibangun.
Dari faktor internal, persma harus menegaskan kembali sikap untuk menjaga momentum kebebasan pers. Ikut menyuarakan kasus majalah Lentera misalnya. Peran ini dapat diimplemantasikan dalam terbitan. Pers umum sudah larut dalam gejala kapitalisasi, maka pers kampus jangan sampai tertidur, masyarakat pembaca butuh alternatif bacaan akibat pola pemberitaan talking news.
Persma perlu mengusung pemberitaan yang berbasis pada penguatan isu dan dinamika politik lokal, seperti komersialisasi pendidikan, otonomi kampus, pemerintahan daerah. Berkonsolidasi dengan organisasi yang bersentuhan dengan basis pemberitaan perlu dilakukan. Isu-isu krusial yang bersentuhan langsung dengan kaum tertindas harus terus angkat.
Pimpinan kampus harus siap menjadi pihak pelindung sekaligus pihak yang akan menjadi sasaran berita. Tentu bukan perkara mudah, saat berita yang diangkat berkaitan dengan berbagai kebijakan pendidikan dilingkungan kampus yang dinilai bermasalah, pihak kampus harus siap menerima. Menjadikan terbitan persma adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan menyalurkan pikiran. Kampus adalah wadah untuk itu. Mencederai kebebasan persma – bagian dari kebebasan berekspresi – sama saja mencederai hak fundamental. Sebuah hak yang dijamin oleh negara yang menjunjung hukum dan hak asasi. Apalagi sampai kehilangan wadah kritis hanya karena ketidaksanggupan menerima kritik. Persma perlu berbenah diri, dan pimpinan kampus harus siap menerima pembenahan diri itu.
Suyadi
*) Pemimpin Umum Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BP2M) Unnes



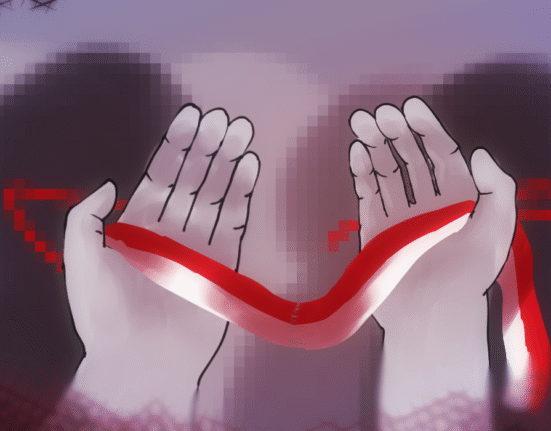

![ilustrasi opini "Informatika: Menyingkap Potensi Pikiran dan Perasaan Manusia" [BP2M/Alya Aisyah]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2025/01/1-551x431.png)
![Ilustrasi "Perempuan Di Ambang Pilihan" [BP2M/Alya]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2024/12/Ilustrasi-perempuan-551x431.png)
![Ilustrasi Opini "Korupsi, Kelompok Aksi, dan Peran Pers" [BP2M/Hanna]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2024/12/ilustrasi-korupsi_20241206151553-551x431.png)