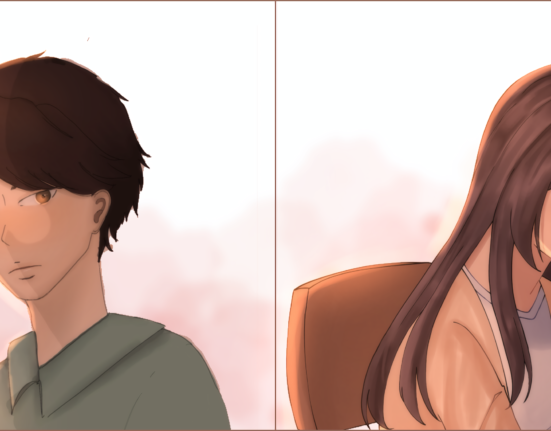|
| crystalgraphics.com |
Malam ini tidurku dirumah tak akan nyenyak. Tidak ada yang lebih menakutkan dari sosok cemas yang menggerogoti hati. Kini cemas berubah jadi hidup dan tak terkendali. Mondar-mandir tak menentu memenuhi seisi otak. Akhir-akhir ini cemas sering berkunjung, entah hanya ingin menjadi aku atau menjadi dia.
Pagi cemas mengucapkan selamat datang dengan wujud yang berbeda pada siang hari. Sore hari cemas lebih kuat lagi mengais perasaan. Beranjak malam cemas sudah tidak bisa berkompromi. Sayangnya aku sudah terlanjur bersahabat dengan cemas, aku kian susah membedakan mana cemas dan mana diriku sendiri.
Aku kurang bisa memastikan penyebab cemas ini datang dengan berbagai wajahnya. Terlebih telah banyak masalah yang bertalu-talu. Ayahku yang tiba-tiba sakit dan sahabatku yang meninggal tetapi belum diketahui akibatnya.
Aku berharap cemas ini tak berujung stres apalagi depresi. Untuk menghilangkan rasa takutku itu aku menyempatkan pergi ke atas bukit yang tak jauh dari rumah. Untuk menghilangkan penat dari hiruk-pikuk kota perantauan, aku menyempatkan pergi ke puncak bukit Pulut untuk melihat senja. Sejak kecil aku sudah tergila-gila pada senja.
Bagiku senja adalah layar raksasa yang diciptakan Tuhan untuk dinikmati meski beberapa detik. Kehadiran senja yang singkat tentu tidak mengecewakan. Warna keemasan dan jingga menghasilkan perpaduan warna merah dan ungu yang mampu menyelimuti jagat raya degan cahaya yang menyilaukan. Aku lebih menyukai senja daripada Fajar. Meski mereka berdua tidak jauh berbeda tapi aku tidak berpihak pada fajar. Senja disaksikan orang-orang yang putus asa atas hari yang ia jalani sejak tadi, untuk menenangkan bahwa ia baik-baik saja. Berbeda dengan Fajar. Fajar hadir untuk orang-orang yang ditakdirkan bahagia. Sehingga dia tidak bahagia karena fajar, tapi bahagia karena dirinya sendiri.
Sembari menunggu mas Dante sampai rumah, aku duduk berhadapan dengan ayah di depan rumah. Duduk di hadapan ayahku yang sedang sakit rupa-rupanya cukup membuatku muak dan ternganga. Ini itu sudah tidak mampu. Coba lihat dulu, kurang kuat apa sosok ayahku ini. bahkan Tuhan masih memberinya hidup daripada temanku L yang satu minggu lalu masih sehat wal’afiat, ditemukan meninggal di kamarnya tanpa sebab. Sungguh misteri suratan Tuhan.
“Yah, karena mas Dante sudah sampai rumah, bolehkah aku kembali lagi untuk kuliah? Sungguh menjadi mahasiswa tidaklah gampang yah,” aku berdiri dengan tas ranselku setelah ku salami mas Dante.
“Sesiang ini ? bahkan hampir sore nduk. Nanti terlalu malam sampai di kos,” ayah mengernyitkan alisnya.
Jam dinding rumah menunjukan pukul dua. Jika dikira-kira aku akan sampai kos pukul 6 sore. Ini tidak masalah asal jangan sampai gelap. Mataku yang sudah tiga bulan buram ini masih bisa berkompromi. Jika aku berkendara sampai gelap bisa fatal. Mereka-mereka yang egois saat berkendara saat malam hari seharusnya sadar akan kondisi pengendara motor sepertiku.
Mereka bisa mengganti lampu jarak jauh mereka dengan lampu biasa agar tidak menyilaukan pengendara yang diseberangnya. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri agar bisa melihat jalan hingga jarak jauh, tetapi akan sangat menderita orang-orang sepertiku. Melihat lampu-lampu mobil yang sangat silau seperti ditusuk mataku sampai dalam. Tak jarang aku menutupinya dengan sebelah tanganku. Tentu ini sangat berbahaya untuk berkendara, terutama jalan-jalan yag tidak terdapat lampu-lampu jalannya.
Ku kenakan semua perlengkapan berkendara. Helm, jaket, sarung tangan yang bolong diujung jarinya, dan sepatu lengkap sepasang dengan kaos kaki.
“Hati-hati dijalan nduk, jangan ngebut-ngebut karena kamu sendirian. Ingat kalau dengar adzan berhentilah kemudian cari masjid atau mushola untuk sholat,” ujar ibuku dengan wajahnya yang sedikit tidak rela melepasku pergi.
Akupun hanya mengangguk dan tersenyum pada ibu. Ayah tak banyak bicara, ia memandangiku dari jauh. Mas Dante tidak kupamiti karena ia juga pasti lelah karena baru sampai.
Hari ini cuaca tak secerah biasanya, cenderung mendung. Aku sedikit khawatir jika turun hujan.
“Mengapa awan tidak menghendaki aku pergi. Aku pergi untuk menuntut ilmu, pergi lagi ke perantauan untuk kuliah. Apakah perjalananku yang mulia ini hanya disuguhi awan yang hitam, wahai langit?” Aku mulai mengoceh dalam hati sambil menikmati angin yang dingin. Selama perjalanan kabut putih itu juga menemaniku. Ia begitu halus, tetapi juga dingin. Ia sedikit menggodaku saat perjalanan.
“Tak perlu buru-buru wahai gadis yang bermata bulat. Nikmati saja kesejukan ku sebentar. Kau hanya bisa menikmatiku kurang lebih 7 km dan tidak lebih lama dari satu jam,” Sejuk yang dia bilang berbisik di telinga, sekaligus menyempitkan jarak pandangku yang hanya mencapai 15 meter.
Rupanya telah usai ku nikmati kabut itu. Selamat tinggal. Tunggu, siapa lagi itu yang menunggu. Ah rupanya jalan yang berkelok itu.
“Selamat datang duhai gadis yang berjari lentik. Pastikan jari-jarimu terjaga di pedal rem. Sungguh aku sangat berbahaya. Aku tidak hanya berkelok-kelok tapi aku menjulang naik, dan berturunan curam pula,” sambutan yang semburat pada tikungan yang pertama.
“Oh jalan yang berkelok, menjulang dan curam pula berikan aku senja. Aku telah melewati awan yang mengerikan, kabut yang kejam, dan kau yang menantang, Aku minta kau berikan aku senja. Beri kesempatan aku entah seberapa detik. Sungguh aku dalam keadaan kacau saat ini.” Aku terus bersua pada alam diperjalananku kali ini.
“Berjalanlah terus gadis Pulut, tidak jauh lagi kau akan berjumpa dengan senja. Ia memang telah menuggu sejak terbenamnya kemarin. Kau cukup lama diperaduan rupanya.”
Benar saja yang dikatakan jalan berkelok itu. Senja telah menungguku. Senja yang mulai menyapu awan. Langit berwarna jingga dan aku terpesona oleh rembulan yang terbit dari balik gunung. Rembulan yang kemerah-merahan, dalam sapuan senja keungu-unguan, membakar langit yang memenuhi semesta. Sungguh semesta sedang berbahagia detik ini, diselimuti senja yang begitu hangat dan dingin pula.
“Duhai senja, jangan kau panggil dulu petang. Biarkan aku bersua sejenak denganmu. Sungguh kini cemas telah menjadi diriku.”
“Begitu beruntungnya kau gadis yang lesung pipinya bisa bertemu denganku. Bukannya kau dilarang bertemu denganku ? ihwal cemas aku sudah terbiasa. Banyak sudah manusia yang aku bahagiakan hatinya hanya dengan pesonaku ini untuk melupakan cemasnya. Apakah sudah hilang cemasmu setelah melihat aku ?”
“Ya, begitulah aku seperti manusia yang lain, wahai senja. Aku begitu terpukau dengan pesonamu di balik dedaunan yang tersentuh kabut dan angin. Tetapi aku tetap cemas. Dalam hitungan detik kau akan menghilang. Dan kau tau siapa yang kan datang? Ya, petang. Sungguh aku tidak ingin bertemu dengannya. Aku bisa mati dibawanya, duhai senja.”
“Maka dari itu cepatlah sampai tempat tujuanmu, wahai gadis yang kini sendirian. Jangan terlalu berlarut kau nikmati aku. Aku akan berubah dengan sekejap mejadi petang. Aku akan berubah menjadi yang tidak kau hendaki dan kau benci. Sungguh aku akan benar-benar melukaimu. Itu lah sebabnya mengapa Tuhan hanya menciptakan aku sebentar, karena manusia selalu serakah menikmati kebahagiaan. Petang adalah jawaban dari keserahan mereka yang telah menikmati pesonaku. Kau tidaklah sekuat mereka, wahai gadis berpupil coklat. Bahkan pupilmu sudah muak dengan cahaya kendaran manusia-manuisa itu kan ?”
“Siapa yang harus meninggalkan dan ditinggalkan, wahai senja. Diriku atau dirimu?”
“Jika aku yang meninggalkan dirimu gadis Pulut, kau yang akan mati. Tetapi jika kau yang meninggalkan aku, maka aku yang akan mati.”
Kematian adalah bagian dari kehidupan. Jika kematian itu hidup, lalu untuk apa kehidupan. Jika semuanya telah menjadi suratan, apa yang masih menarik dalam kehidupan. Bahkan Senja hanya hidup dengan sesingkat itu. Sebelum ia lahir kembali, Apa yang dia perbuat saat menjadi Fajar ? Petang ? Sungguh ini adalah suratan Tuhan.

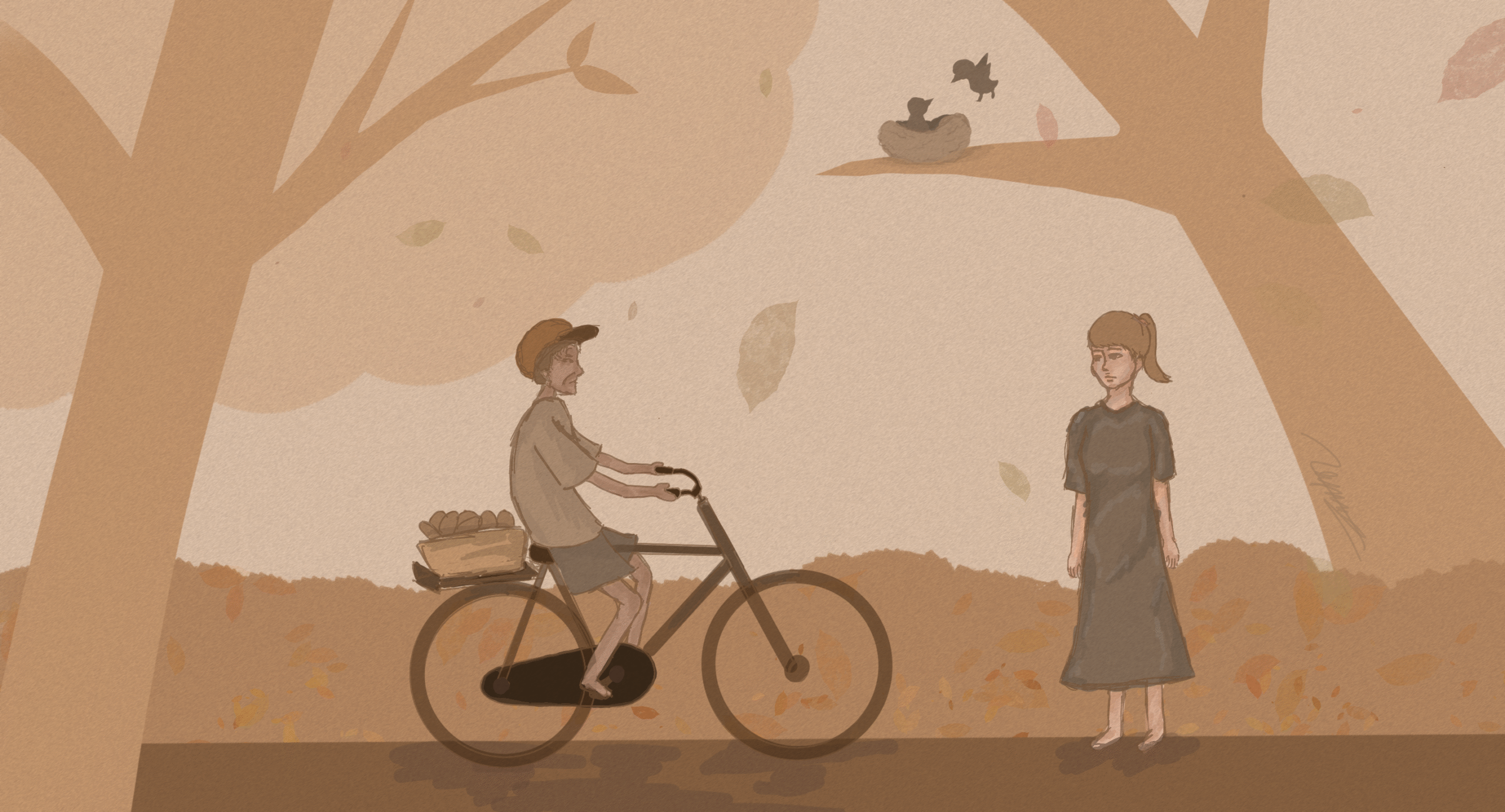
![Ilustrasi Puisi “Lembar Koda Sang Pecundang” [BP2M/Hanna Watsiqatul Fadha'il]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2025/03/1-551x431.png)