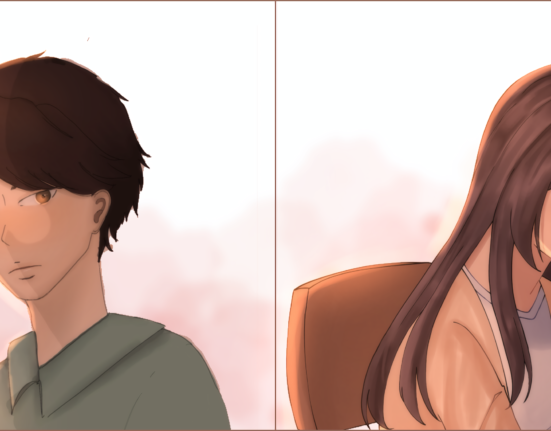|
| Sumber: http://gobekasi.pojoksatu.id/ |
Teras halaman rumah masih menjadi tempat favorit ibu menghabiskan malam. Ibu selalu duduk termangu memandangi rembulan sembari menyeruput teh hangat pahit yang setia menemani. Kadang aku mereka-reka apa yang dipikirkannya. Entah hingga kini tak dapat ku pahami. Kerap kali aku hanya sekadar menyapa dan bertanya, “Bu, lagi mikir apa? Kok bengong aja. Hehe.” Ibu hanya membalas dengan senyum tipis dan tidak banyak kata terucap dari bibirnya.
Usai kepergian bapak, ibu memang berubah perangainya. Lebih suka merenung dan hening. Padahal ketika ada bapak, ibu lebih ceria. Malam-malamnya dihabiskan dengan bersenda-gurau bersama Renai, adikku satu-satunya sembari menanti bapak pulang kerja. Tapi itu dulu. Keceriaan itu kini tak dapat ku jumpai lagi.
Bapak pergi meninggalkan keluarga kecilnya tepat setelah wisuda kelulusanku di SMA. Kecelakaan menimpa bapak saat bekerja di depan stasiun. Sebuah mobil yang dikemudikan pemuda mabuk dengan kecepatan tinggi menabrak bapak serta gerobak gorengan dagangannya. Pemuda tersebut lantas dihajar warga sampai meninggal. Pemuda itu menyusul kepergian bapak.
Entah aku heran dengan warga saat itu yang berani main hakim sendiri sampai membuat nyawa orang melayang begitu saja. Andaikan pemuda tersebut masih hidup, mungkin kini ia akan menjadi sahabatku. Aku senang dengan orang-orang semacam itu. Senang dalam artian aku memiliki lahan untuk bisa menjadi orang bermanfaat, menjadi manusia yang mampu merangkul pemuda yang krisis identitas untuk mampu menemukan identitas sejatinya.
Tapi apa daya, manusia saat ini kala menemui pemuda mabuk, pencuri, atau pemerkosa, pasti yang mereka lakukan adalah: hajar sampai habis! Padahal sadar tidak sadar, jika manusia yang memiliki nurani, pasti anggota tubuh yang paling peka menghadapi hal tersebut yakni pundak. Pundak untuk merangkul dan membimbing menuju ke jalan yang baik. Bukan malah kaki atau tangan yang digunakan untuk menghajar.
Malam ini tampak berbeda, ibu tak terlihat di teras rumah. Aku cari di dalam rumah pun tak kelihatan.
“Nai, ibu kemana ya?” ku tanya pada adikku.
“Renai kurang tau, Kak. Ibu dari sore pergi dan sampai sekarang belum pulang,” balasnya apa adanya.
Aku mulai berpikiran tak karuan. Jam sudah menunjukkan pukul sembilan malam dan ibu masih di luar rumah. Setahuku ibu tidak suka bepergian malam-malam, tapi mengapa kini ia memberanikan diri keluar malam?
Dengan langkah gelisah ku coba mencari ibu. Beberapa tetangga ku tanya pun tak mampu menjawab. Hingga pada akhirnya, ku temui ibu di Warung Makan Padang Sejahtera, tempat kerjanya dahulu.
“Lho, ibu kok malam-malam masih di sini?” ku tanya ibu seketika dengan nada sedikit cemas.
“Nak, kamu ngapain malam-malam masih kelayapan? Adik kamu kok ditinggal sendirian di rumah?” balas ibu mencoba mengelak dari pertanyaanku.
“Bu, mending pulang yuk. Sudah malam,” ajakku memelas.
“Belum bisa, Nak. Ibu masih harus kerja. Belum boleh pulang.”
“Ibu di sini kerja lagi? Kan Bayu sudah bilang, ibu tidak perlu bekerja. Biar nanti Bayu saja yang mencari uang buat ibu dan Renai. Ibu sudah istirahat saja.”
Aku tidak menyangka, ternyata ibu kembali bekerja di sana.
“Maaf, Nak. Ibu tidak bisa lepas tanggung jawab. Renai butuh uang untuk study tour sekolahnya. Listrik kita juga sudah nunggak lama.”
“Kok bisa, Bu? Waktu itu uang yang Bayu kasih kemana?” tanyaku heran.
“Sudah ibu gunakan untuk membayar hutang bapakmu, Nak. Sudah habis.”
Aku bingung mengapa ibu tidak bilang saja kalau ternyata sedang butuh duit. Kalau tahu begitu aku memilih cuti kuliah dan bekerja lebih keras setiap harinya. Biar malam harinya aku menjadi pelayan di kafe, siangnya kuhabiskan mencari kerjaan yang lain ketimbang duduk di bangku kelas sedangkan ibu memikirkan banyak hal yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawabku.
Entahlah. Aku terus membujuk ibu dengan berbagai cara. Namun tak mampu meluluhkan hatinya supaya mau pulang. Akhirnya aku pasrah dan tak ingin memaksa ibu. Aku memilih pulang dan menemani adikku di rumah seorang diri.
Saat kuliah aku mulai merasa lesu. Herman teman satu kampus yang memahami keadaanku lantas menyapa.
“Bay, mau kemana? Suram amat tampang lu,” selorohnya asal. “Nanti malam free nggak? Main yuk ke rumah gue,” jelasnya sembari mengajakku main bersamanya.
“Ngapain, Man? Tumben nawarin gue main ke rumah,” tanyaku penasaran.
“Udah nggak usah banyak tanya. Main aja.”
“Maaf, Man. Gue nggak bisa. Gue kan kerja di kafe kalau malam, cari duit. Adik gue lagi butuh duit banget.”
“Butuh berapa sih? Ayolah main sekali-kali. Kalau lu main, nanti kebutuhan adik lu gue kasih deh. Tinggal ngomong berapa butuhnya. Buat malam ini lu izin kerja aja dulu.”
Tawaran Herman lantas membuatku berpikir, tampaknya tawaran tersebut cukup menarik dan membantu. Herman memang anak konglomerat yang uangnya berlebih. Sayangnya uang tersebut biasa digunakan untuk berfoya-foya, seperti ke bar, karaoke, dan hal-hal buruk lainnya.
Aku sempat berpikir apa jangan-jangan di rumahnya nanti malam akan diadakan pesta ulang tahunnya? Sebab hari ini adalah hari ulang tahunnya. Ku pikir jika aku ikut sama saja aku ikut budaya yang tidak diajarkan oleh agamaku. Tapi jika menolak, mau kemana lagi aku mencari duit untuk membayar study tour Renai dan tunggakan listrik rumah? Ah, mungkin hanya prasangkaku saja. Mungkin saja Herman mengajakku ke rumahnya untuk belajar bersama.
“Iya deh, Man. Nanti gue main ke rumah lu. Tapi bantu kebutuhan adik gue ya?”
“Siap. Gue tunggu, Bay.”
Deal! Aku menyepakati. Di satu sisi karena kebutuhan, namun di sisi lain aku juga ingin lebih dekat dengan Herman. Karena dengan dekat dengannya maka sama saja dengan mempermudah langkahku untuk menjadikannya pribadi yang lebih baik dibanding sebelumnya yang suka berfoya-foya, pikirku.
Aku kembali ke rumah. Tampak gelap dan hening. Saat aku masuk ke rumah, ku lihat Renai sedang istirahat ditemani sepotong lilin yang menerangi ruang. Sepertinya listrik rumahku sudah dicabut karena telah menunggak pembayaran cukup lama. Melihat keadaan tersebut, membuat kehendakku untuk bermain ke rumah Herman semakin bulat.
Sehabis mandi dan rapi-rapi, aku bergegas ke rumah Herman. Sesampainya di rumah Herman, aku tercengang. Di sana sudah ramai teman-teman Herman bergoyang diiringi musik elektro yang menggema. Ternyata dugaanku benar, Herman sedang mengadakan pesta ulang tahunnya.
Teman-teman wanita Herman mulai menghampiriku dan mulai menggoda. Secara tidak sengaja, sesuatu bungkusan kecil jatuh dari kantong celana teman wanita Herman. Aku pun sigap mengambil dan ternyata barang tersebut adalah ekstasi. Aku yang sudah hilang kesabaran lantas naik ke atas panggung dan menasihati sekaligus mengancam mereka untuk segera membubarkan pesta, karena jika tidak maka akan kupanggil polisi.
“Bay! Gak asik banget lo!” bentak Herman diikuti suara sorak-sorai teman-teman Herman memaki-makiku dengan berbagai kata tak sopan.
Dengan ancamanku yang serius, akhirnya tidak lama berselang pesta dibubarkan, meski resiko yang kuterima yakni aku dikucilkan dan dianggap manusia kuno bagi mereka. Tapi biar saja, aku anggap itu sebagai proses pendewasaan mereka supaya mereka paham apa yang mereka lakukan salah.
Sesudah kejadian itu, aku pulang ke rumah. Ku lihat banyak warga berkerumun dan rumahku sudah terbakar hangus. Bencana kebakaran menimpa rumahku. Aku yang tak kuat menahan cemas, berusaha menerobos kerumunan warga untuk melihat kondisi Renai.
Namun sial, Renai sudah tiada. Kepergiaan Renai membuat ibu jantungan dan turut menyusul Renai meninggalkan dunia ini. Kini semua keluargaku telah pergi kepada Sang Pemilik. Ini sudah takdir dan sebagai hamba, aku harus mampu ikhlas menerima.
Aku jadi teringat lilin di kamar Renai. Dari sana aku terinspirasi untuk menjadi seperti lilin, yang akan menerangi dunia ini dengan apa-apa yang ku bisa. Mimpiku setelahnya, aku ingin menjadikan Herman dan teman-temannya mampu menerangi jiwanya yang sebelumnya gelap.
Aku ingin menjadi lilin, yang mampu menjadikan pemuda-pemuda akhir zaman lainnya menjadi lilin pula. Meski pada akhirnya aku tahu, akan ada masanya lilin itu mati, habis, dan tidak meninggalkan sisa. Namun, setidaknya ketika ia habis, ia telah menyalakan lilin-lilin lainnya dan menerangi dunia yang sempat gelap.

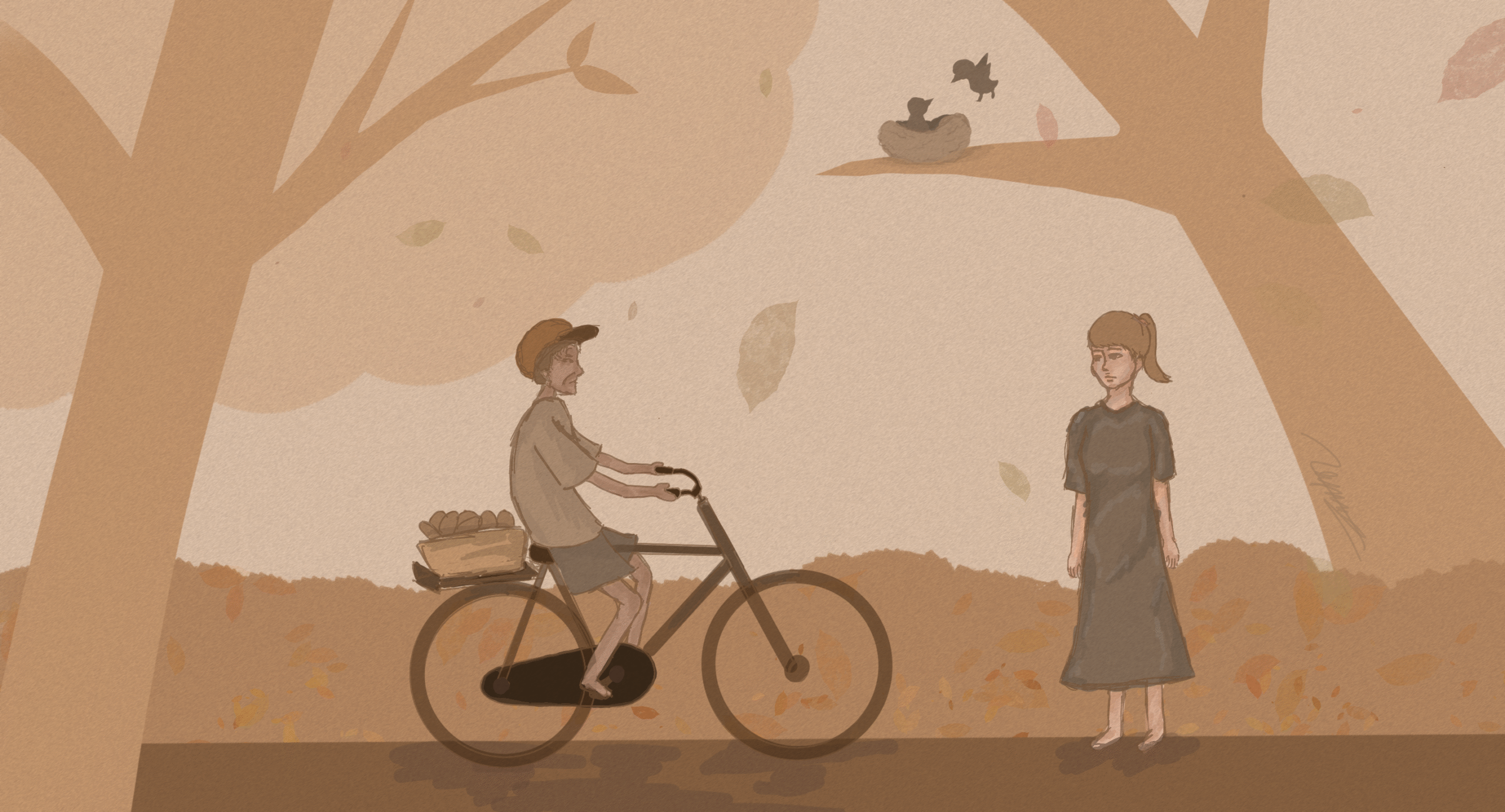
![Ilustrasi Puisi “Lembar Koda Sang Pecundang” [BP2M/Hanna Watsiqatul Fadha'il]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2025/03/1-551x431.png)