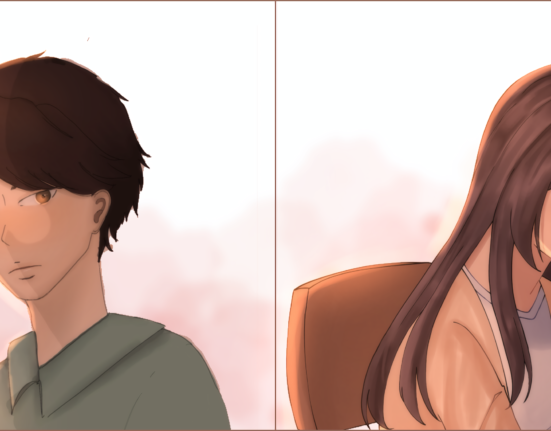|
Sebuah sumur tua sebelah rumah Nadir tiba-tiba ramai diperbincangkan warga. Bahkan saking tiba-tiba nya Nadir hanya gelagapan ketika ditanya Mbah Siman, sang Tetua kampung mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada sumur tua itu. Nadir tak bisa bicara dengan jelas, hampir semua kalimatnya tak rampung diucapkannya dan selalu diam yang lama seolah berfikir tapi ketika ditunggu tak kunjung muncul kalimat juga.
“Nganu, Mbah, nganu” kata Nadir yang lagi-lagi hanya lancar pada kata ‘nganu’. Nadir terlihat tidak merasa nyaman karena sesuatu. Matanya selalu tidak fokus, keringat dingin membasahi keningnya. Kaos biru bergambar barong Bali yang dikenakannya dari lusa itu mulai basah.
Aku masih tidak mau berfikiran buruk pada Nadir, tapi melihat gelagatnya siapapun yang hendak percaya rasanya akan berfikir ulang. Nadir bukanlah orang yang akan bertindak ceroboh meskipun ia terkesan tertutup. Biasanya orang tertutup mudah melakukan hal-hal diluar dugaan akibat tidak punya tempat curhat. Aku tidak hendak memukul rata, tapi itulah kata Ayah sebelum meninggal kemarin lusa.
“Dir, mbok ya bilang opo seng mbok weruhi Soko kedadean Iki to, kari ngomong lo. Opo wae” kata Mbah Siman sembari mengelus pundak Nadir.
Baca Juga Cerpen: Mirat
Nadir sama sekali tidak terlihat lebih tenang. Sesekali ia terlihat menerawang, kami menunggu. Lama, Nadir masih diam saja. Ketika ditegur Nadir menunduk, seperti hendak menangis tapi tak terdengar isakan atau terlihat air mata yang jatuh.
Mbah Siman kemudian menyuruh kami yang menonton didepan rumah Nadir pulang, sementara ia dan Nadir masuk kerumah dan menutup pintu. Warga yang kecewa menumpahkan kekesalannya pada orang disebelah kanan kirinya. Aku yang tepat di samping Mbak Jah untungnya malah menanyakan ibuku dan tidak mengungkit persoalan Nadir.
“Lin, ibukmu wes muleh urung?” Tanya Mbak Jah.
“Palingan uwis, Mbak” jawabku dengan sedikit ragu, kemarin ibu pulang jam 12 siang, mungkin hari ini juga pulang pada jam yang sama.
Sehari yang lalu semua warga masih tak menghiraukan keberadaan sumur itu, pemuda seumuran ku pun hanya sedikit yang tahu. Kini dari emak-emak yang tidak suka bergosip sampai bocah ingusan membicarakannya.
Awal munculnya pembicaraan wajib kampung ini bermula ketika ada mobil hitam mengkilap parkir di depan rumah Nadir. Pembicaraan waktu itu hanya sekedar penasaran biasa warga kampung mengenai orang asing yang memasuki kampung mereka. Wajarlah sangat jarang ada orang luar kampung yang bertandang apalagi dengan logat orang kaya seperti penumpang mobil hitam mengkilap itu, pastilah menarik perhatian warga kampung.
Mobil hitam mengkilap tak lama parkir di sana. Aku mendengarnya dari Mbak Ani yang berada di emperan rumahnya ketika mobil parkir dan masih disana ketika mobil meninggalkan pekarangan rumah Nadir.
“Mobile ora sui, paleng limolas menitan.”
Baca Juga Cerpen: Ziarah
Rumah Mbak Ani tepat di depan rumah Nadir membuatnya menjadi sumber utama informasi dan yang paling sering ditanyai warga ketika sedang membicarakan hal ini. Seperti saat ini, ada yang sedang membicarakannya lagi di depan rumahku. Aku memasang telinga lebar-lebar dari dalam bilik kamar dekat ruang tamu, meski begitu aku masih mendengar jelas pembicaraannya.
“Piye An, mobile? Kok Yo lagian ngomong nak sak durunge enek mobil” terdengar suara ibuk.
“Walah Yu, maleh mbaleni meneh to, males aku, Kono Jah ceritakno” kini aku hafal sekali bahwa itu suara Mbak Ani kepada Mbak Jah.
“Wong-wong Ki Yo wes ngerti Ono mobil, ndek ingi Ki Yo rame kok. Sampean Iki to seng kerjo wae, dadi ne Yo Ra ngerti opo-opo” ujar Mbak Jah.
Ibu mulai bekerja setelah ayah meninggal. Ibu bekerja di rumah Bu Riyan, mengasuh anaknya yang tahun ini masuk paud sementara Bu Riyan bekerja di Bank.
“Lha terus piye neh Olin arep melbu SMA butuh duit akeh” kata ibu dengan nada merendah seolah menyayangkan sesuatu.
“Tapi kok aneh ya, mosok Nang sumur ujug-ujug Ono…” Ucap Mbak Jah belum selesai merampungkan kalimatnya Mbak Ani tiba-tiba menyapa Mbah Siman yang sepertinya lewat.
“Monggo Mbah Man” sapa Mbak Ani. Tapi sepertinya Mbah Siman tidak menyahut balik.
“Kok kesusu men, arep nang ndi Mbah?” Kini yang terdengar suara ibuku. Seperti nya lagi Mbah man tidak menjawab.
Baca Juga Cerpen: Lilin di Akhir Zaman
Aku akhirnya harus kecewa ketika yang dibahas selanjutnya malah Mbah Man dan masa lalu Nadir yang punya riwayat gila. Lalu orang-orang mulai menyangka bahwa Nadir kumat dan melakukan hal itu karena sedang kumat. Aku masih menunggu kelanjutan cerita soal sumur tapi tak kunjung dibahas.
Adzan asar berkumandang, bergosip sudah harus bubar. Berarti kini waktunya aku keluar kamar.
“Lin, Ndang adus. Terus Nang masjid Yo Le” kata ibu sambil mengambil sapu dibelakang pintu.
“Nggeh, Bu” aku lantas mengambil handuk mandi.
Letak masjid tidak terlalu jauh, tapi aku harus melewati rumah Nadir. Ah, semua yang berbau Nadir kini tak nampak biasa-biasa saja. Biasanya aku bahkan sempat menyapa Nadir yang duduk didepan rumahnya atau sesekali mengobrol dengannya kini aku rasanya agak enggan yang entah karena apa.
Nadir setahun lebih tua dariku, jika bersekolah dia pasti sudah masuk SMA. Nadir tinggal sendiri.
Ibunya bekerja ke kota, entah kota yang mana. Yang jelas ibunya tak pernah lagi pulang. Sementara ayah Nadir meninggal dua tahun lalu, dan ibu Nadir masih tidak pulang ketika ayah Nadir meninggal. Karena depresi inilah, warga menyebut Nadir gila. Bahkan, aku juga tidak lagi datang kerumahnya ketika dia gila. Hanya Mbah Siman yang rajin datang dan sesekali menginap. ayah juga terlihat sesekali datang ketika hendak berangkat bekerja dan tak jarang membagi makanan kami untuk Nadir.
Baca Juga Cerpen: Sepotong Roti Sobek
Terdengar suara iqomah dari masjid, aku lekas berlari. Untunglah imam belum memulai sholatnya.
“Mari bapak-bapak shafnya dirapatkan” kata ustadz Fi’an.
Seusai sholat ashar aku merasa enggan pulang ke rumah, dan memilih duduk-duduk di Selasar masjid.Aku lagi-lagi mendengar nama Nadir disebut, aku juga mendengar suara ustadz Fi’an nimbrung.
“Iya ustadz, kemarin sore itu di dekat sumur Nadir ada box bayi agak lusuh plus perlengkapannya. Tapi bayinya kagak ada.” ucap kang Rido.
Ustadz Fi’an orang kota jadi siapapun yang berbicara dengannya harus berbahasa Indonesia. Karena sebab itu juga lah aku malas banyak bicara dengan ustadz karena bahasa Indonesia ku terdengar aneh ditelinga.
“Yang menemukan pertama kali siapa, Un?” Tanyanya pada Mi’un.
“Biasalah emak-emak sini, makanya langsung heboh gini,” jawab Mi’un.
“Boxnya nggak cuma lusuh, tapi kaya ada noda darah banyak banget.”
“Kamu lihat boxnya?”
“Enggak sih tad, tapi banyak orang yang bilang gitu.”
“Terus nih tad, ada mobil hitam didepan rumah Nadir di siangnya dan sorenya ditemukanlah sebuah box itu”
“Orang-orang sih curiga kalo bayinya ada di sumur, tapi orang-orang kaga ada yang berani liat.”
“Bayi siapa?” Ucap ustadz dengan sedikit bercanda
“Engga tahu, tapi Nadir juga gelagatnya mencurigakan sih.”
“Eh, sudah. Kok malah nggosipin Nadir, ini di masjid lo. Malu didenger sama Allah. Sesama saudaranya kok saling mencurigai gitu, lebih baik kita tanya langsung ke Nadirnya.”
“Sudah pak ustadz, tapi Nadir gagu pas ditanya Mbah Man.” timpal Mi’un tak mau kalah.
“Loh Lin, belum pulang” ucap ustadz Fi’an yang tiba-tiba ada di sampingku.
“Belum ustadz, iseh betah” jawabku sekenanya.
“Ya udah, saya pulang dulu ya.”
Baca Juga Cerpen: Mengejar Senja Sebelum Petang
Aku mengangguk kan kepala. Aku memperhatikan ustadz Fi’an dari kupluk sampai sandal jepit yang ia pakai. Terlihat bagus walau sederhana. Lalu aku memperhatikan Mi’un dari ujung rambut (Mi’un tak pernah memakai kupluk ketika sholat) sampai ujung sandal jepitnya. Mengapa seorang ustadz terlihat pantas walau kutahu pakaian Mi’un lebih mahal. Sandal jepit mereka merk-nya sama tapi tadi kulihat punya ustadz terlihat lebih enak dipandang. Apa karena ustadz atau pandanganku saja.
Mi’un masih mengoceh meski pak ustadz Fi’an hanya tertawa jengah dan sesekali mengangguk. Terlihat sekali ustadz tidak tertarik tapi Mi’un terlihat tidak menyadari.
Sandal jepit, sandal jepit, sandal jepit, sandal jepit, sandal jepit pak ustadz Fi’an masih berputar-putar dikepalaku.
“Gosip Iku kok koyok sandal jepit ya.” kalimat itu tercetus begitu saja, aku terkejut ketika itu terucap dari bibir tak hanya dipikiran ku saja.
“Kok bisa.” tanya pak ustadz Fi’an yang muncul dari dalam masjid.
“Lo ustad kok disini lagi?”
“Tas saya ketinggalan, kamu ngelamun sih jadi nggak liat saya balik lagi” ucap ustadz sambil ikut duduk di sampingku.
“Kenapa gosip kaya sandal jepit, Lin?”
“Enggak apa-apa ustadz, saya ngasal ngomong saja.” jawabku dan langsung beranjak pergi.
“Saya pulang Tad, assalamualaikum”
Tak cuma jalan aku bahkan lari. Bahkan aku tak sempat mendengar salam balik dari ustadz Fi’an.
Aku terhenti ketika melihat mobil polisi di depan rumah Nadir. Tak kulihat sosok Nadir. Warga sudah memadati rumah Nadir. Sesaat kemudian terlihat Nadir keluar rumah dan dibelakangnya ada orang asing yang terborgol tangannya. Perempuan yang terlihat lebih muda dari ibuku, kira-kira seusia Mbak Jah.
Nadir, Mbah Man dan orang itu masuk ke mobil polisi. Rumah Nadir pun dipagari garis polisi. Astaga, kampung ini akan lebih ramai lagi sekarang. Sandal-sandal jepit yang jarang terlihat akan muncul sebentar lagi. Semua sandal selalu perlu informasi lalu gosip lebih membuat sandal itu betah di tempatnya. Aku harus siap pura-pura tidur sampai ketiduran mulai sekarang.


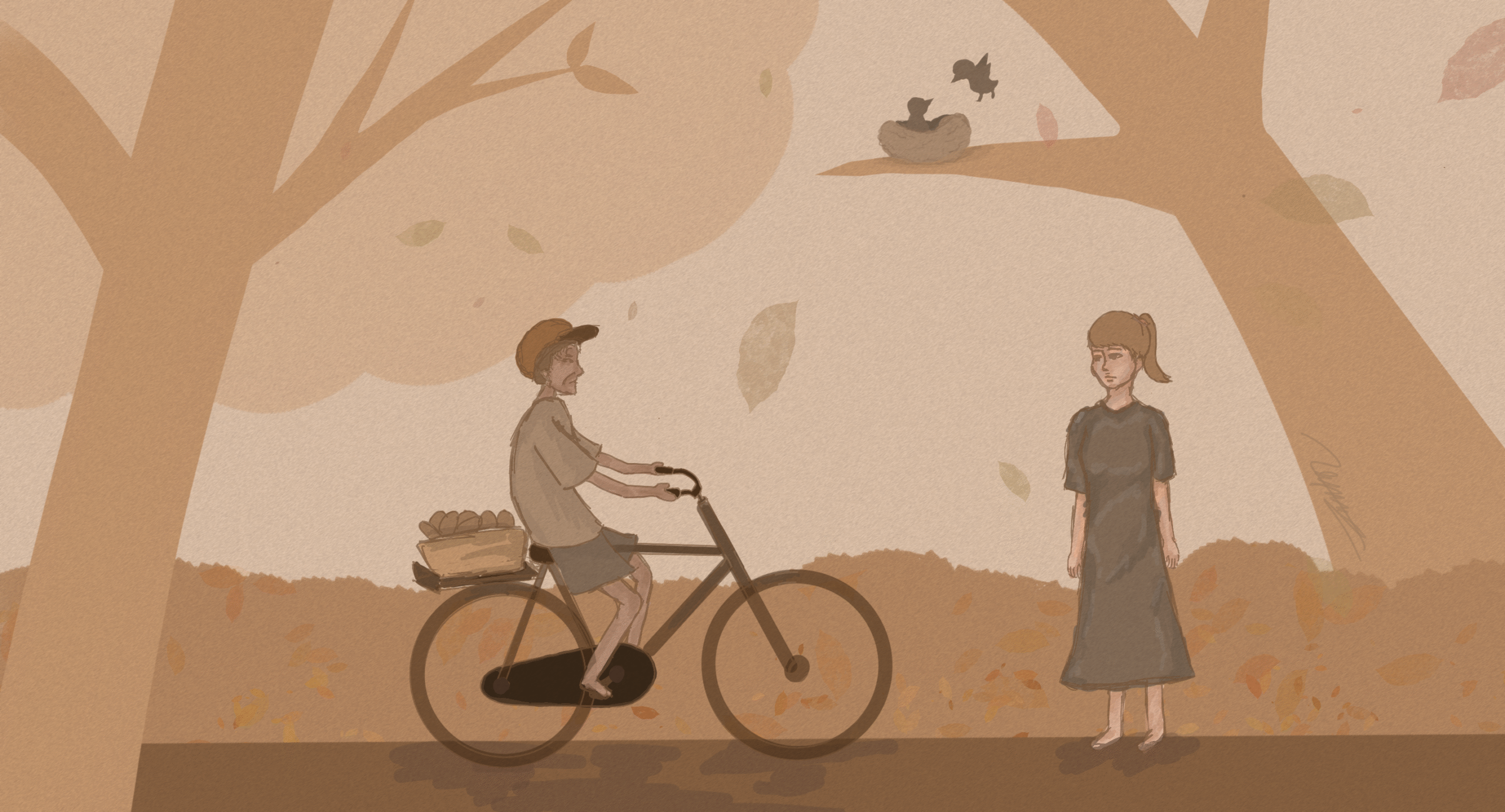
![Ilustrasi Puisi “Lembar Koda Sang Pecundang” [BP2M/Hanna Watsiqatul Fadha'il]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2025/03/1-551x431.png)