Oleh: Lukfi Kristianto
Mahasiswa Ilmu Politik Unnes 2017
Apa itu pemira? Mendefinisikan secara etimologis, ialah akronim dari pemilihan umum raya. Di mana kekuasaan mahasiswa dilembagakan untuk menentukan ‘wakil’ yang bakal memanggul kepentingan sekaligus manifestasi dari daulat mahasiswa.
Secara teknis-elektoral, pemira memang sesederhana itu. Bahwa pemilihan pada pelbagai kategori ormawa (organisasi mahasiswa)—yang entah hierarkis atau koordinatif—semacam tradisi yang kudu ditunaikan tiap tahun. HIMA, BEM, dan DPM yang dipilih langsung oleh rakyat mahasiswa, tiap tahun mengalami sirkulasi dan rotasi kekuasaan.
Konon, lembaga eksekutif dan legislatif tersebut bertanggung jawab kepada mahasiswa, sebab dipilih langsung mahasiswa. Sekilas, ini memang serupa dengan tata sistem politik demokrasi mainstream. Konon lagi, itu dimaksudkan agar mahasiswa belajar mengenai kehidupan demokrasi. Jika betul demikian, maka mahasiswa belajar berbagai peran dalam ‘simulasi’ demokrasi ini, ada calon, ada panitia pemilihan, ada tim sukses, tim gagal, badut, tukang nyiyir wal gossip, dan seterusnya.
Terlepas benar atau tidaknya mitos tersebut, satu hal yang terang adalah terdapatnya praktik dan proses demokrasi politik dalam pemira. Maka, analisis demokrasi yang sedikit serius menjadi layak untuk mengulas lite-democracy ini.
*
Dalam waktu dekat, entah kapan tepatnya, tampaknya pemira akan kembali dihelat. Kasak-kusuk dan desas-desus ihwal pemira mulai terdengar—setidaknya pada lingkaran sosial penulis. Di antaranya tentang “Siapa sih yang bakal maju?” “Eh Si Otong berhenti jualan ayam buat jadi timses!” dan berbagai ungkapan senada.
Seperti perbincangan pemilu pada umumnya dan pemira pada khususnya, hanya berputar pada spiral topik mengenai aktor, pihak kontestan, dan sedikit jauh perihal strategi teknis pemenangan. Tetap redup dan hening pembahasan mengenai topik politik substantif, misalnya tentang wacana, ideologi, dan paradigma politik dalam kontestasi pemira.
Paling mentok pada perbincangan tentang grand design kandidat, yang saking keringnya imaji dan gagasan acap menggunakan istilah-istilah template semacam “sinergitas”, “harmonisasi”, “kolaborasi”, dan segudang istilah aksesoristik nir-makna. Disusul dengan visi-misi normatif asal-asalan biar agak keren dan rancangan program kerja yang secara tidak tahu malu serupa dengan program turunan atau bahkan sesama konstestan, dengan sedikit perubahan pada penamaan.
Sependek telinga penulis, tidak ada sedikit pun diskursus mengenai basis dan suprastruktur politik student government kita. Berkaitan dengan mengapa suprastruktur politik kita hanya menghasilkan habitus seremonialisasi, simulasi, dan penghambaan tradisi? Apa yang salah dengan basis struktur politik kita, di mana apatisme pegiat mobelejen, pegiat traveling dan Instagram, serta penganut anime-isme cukup dominan dalam hegemoni budaya mahasiswa?
Telah banyak disodorkan kepada kita, bahwasanya rekrutmen politik dan pelembagaan kekuasaan lewat pemira hanya membuahkan himpunan yang menjadi tangan kanan kekar jurusan, badan eksekutif yang profesional menyelenggarakan simulasi event organizer, dan dewan perwakilan yang tidak hanya mandul produk legislasi, tapi juga rentan bergaining position-nya.
Tanpa menihilkan jejak kerja sahabat kita, sebetulnya ada beberapa hal yang patut disyukuri. Dijumpainya beberapa pihak yang sadar dalam gerakan penanganan kekerasan seksual dan gerakan ekologis di dalam lembaga kemahasiswaan, ibarat seseorang yang membawa kayu bakar di musim dingin.
Sayangnya, penulis menduga keras keganjilan dalam suprastruktur tersebut tidak merupakan refleksi dari basis.
Dengan mengamini Antonio Gramsci, filsuf neo-marxist Italia, dalam kritiknya terhadap teori basis dan suprastruktur masyarakat Karl Marx, ditambah Laclau and Mouffe yang kemudian turut menyempurnakan teori tersebut. Memang suprastruktur tidak selalu merupakan refleksi atas basis, mengingat terjadi banyak pertarungan hegemoni dan faktor unik personal. Pada kasus gerakan anti kekerasan seksual dan lingkungan hidup ditengarai lebih disebabkan dua topik tersebut merupakan isu dan gerakan global, bukan cerminan kepentingan basis yang menghendaki common goods-nya.
*
Di sisi lain, kita harus mengakui bahwa basis mahasiswa kita cenderung tidak peduli dengan pemira. Hanya dua angkatan aktif yang masih tenggelam dalam gelora per-progjaan saja yang biasanya peduli dengan proses reorganisasi LK tersebut. Keduanya, ialah mahasiswa baru dan mahasiswa tahun kedua. Mahasiswa baru yang mencoba peruntungannya untuk menjadi ‘aktivis’—yang acap merasa tertipu ekspektasinya—dan mahasiswa tahun kedua yang sedang tersedu-sedu menjadi budak progja.
Mahasiswa baru dengan presumsinya mengenai dunia kampus dan rasa keadilan serta ‘idealisme’ tinggi, terbelalak kagum sekaligus penasaran dengan bagaimana aktivisme berkerja. Dilengkapi dengan taburan bumbu oleh kakak-kakak ‘aktivis’ dalam pidato dan aksi teatrikalnya pada pekan pengenalan akademik kampus. Maba semakin membulatkan tekad penuh semangat dan langsung mengidentifikasi bahwa lembaga kemahasiswaan adalah wahana aktivisme. Saking teriknya semangat itu, terlihat running text di jidat mereka, berbunyi “Aku harus seperti kakak itu, keren seperti aktivis orba!”
Begitulah mula cerita, dengan kemudian mereka menilai pemira sebagai langkah besar pertama yang wajib diambil. Beberapa punya nyali menjadi bagian proyek suksesi calon, beberapa hanya digarong KTM-nya dan beberapa dengan nyali serta koneksi kecil hanya bisa mengintip proses politik tersebut. Sampai pada akhirnya mereka sadar, bahwa kakak-kakak ‘aktivis’ keren pada saat PPAK, ternyata mulutnya hanya berisikan sampah dalam orasinya.
Tercengang dengan rahang terjatuh menganga, ketika mengetahui aktivitas harian pada lembaga kemahasiswaan. Sangat kontras dengan penampilan garang dan menyalak saat berorasi, Si Kakak ‘Aktivis’ rupanya hanya cakap berbunyi “Iki konsumsi piye, konsepan acara piye?”
Sedangkan, mahasiswa tahun kedua yang imajinasi ‘aktivisme’ telah lama menjadi puing-puing. Dengan pemahamannya mengenai realita kehidupan lembaga kemahasiswaan, mereka memiliki orientasi yang lebih strategis. Sekelebat ditemui nafsu untuk kenaikan jenjang karir atau jabatan, setelah selama satu periode dengan menyedihkan menjadi staf dengan status sub-ordinat, mereka ingin menjadi kepala departemen!
Konon tradisinya begitu, maka mereka mau tak mau harus terlibat mencari kontrak politik. Prasyarat untuk itu, adalah dengan memenangkan calon, agar status fungsionaris ‘jalur undangan’ lekas dalam genggaman.
Dengan komposisi tersebut, cukup berat untuk berharap basis struktur memiliki pandangan radikal, perihal bagaimana demokrasi substansial direalisasikan, menghasilkan calon yang memiliki manifesto wacana progresif, dan politik intelektualisme organik. Tampaknya, hanya didapati pandangan politik pragmatis-kontraktual pada saat pemira.
Padahal, demokrasi berkerja dengan adanya wacana atau diskursus publik di basis struktur. Diskursus adalah arena atau domain perang gagasan dan pandangan, yang bakal memunculkan diskonsensus/disensus. Meminjam demokrasi agonistik atau demokrasi radikal ala Laclau dan Mouffe, hanya dengan diskonsensus berbagai kompromi dan ‘aturan main baru’ dapat dimungkinkan. Singkatnya, demokrasi membutuhkan geger gedhen pandangan pada basis struktur.
Geger gedhen dalam diskursus merupakan penanda yang dapat dibaca untuk menemukan apa dan bagaimana nalar publik. Di mana itu menjadi modal utama soal bagaimana suprastruktur harus dibentuk—berbanding lurus pula pada bagaimana produk kebijakan dibuat. Selain itu, disensus dalam wacana di basis juga menentukan bagaimana aroma dari ideologi dan gerakan lembaga kemahasiswaan sebagai suprastruktur politik.
Jika basis struktur waras dan sehat, maka tidak mungkin dikehendaki eksistensi lembaga kemahasiswaan yang hanya mampu melaksanakan rupa-rupa warna simulasi dan kegiatan seremonial dengan acuan baku program kerja. Di mana kerap tanpa inovasi dan tanpa refleksi, mengadopsi secara serampangan warisan masa lalu, tanpa mencoba mencerminkan diri pada basis struktur. Jika begitu agaknya cukup mustahil berharap banyak, agar lembaga kemahasiswaan mampu menjalankan fungsi strategis ormawa dalam pengembangan diri mahasiswa ke arah “perluasan wawasan” dan “peningkatan kecendekiawanan” serta “integritas kepribadian” untuk mencapai “tujuan pendidikan tinggi”.
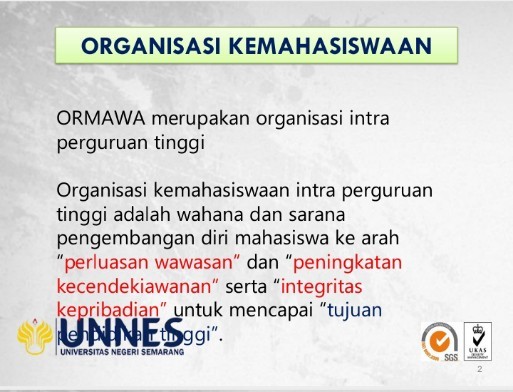
*
Pemira kita semacam panggung komedi belaka. Badut-badut politik yang saban tahun dengan sabar dan istiqamah merawat dan meruwat banyolan dan candaan. Sayangnya, candaan itu sama sekali tidak lucu, bukan saja tidak mengundang tawa, tapi secara langsung menghantam skala terbalik kedongkolan dan kejengkelan.
Melihat komedi yang tidak lucu ini, penulis teringat dengan salah satu wahana di taman-taman bermain atau di pasar malam, yakni komedi putar. Kini, setelah belasan tahun tidak lagi menungganginya, penulis belum menemukan dimana letak kelucuan sekumpulan kuda yang berputar pada bidang datar itu. Satu hal yang pasti, penulis lebih sering mual ketika menunggangi kuda-kudaan warna-warni itu. Jadi memang ada komedi yang tidak lucu, selain sekawanan kuda-kudaan itu, ternyata salah satunya adalah pemira.
Marry Go Round—sinonim komedi putar—tidak asing berbeda dengan pemira. Yakni, sejenis atraksi ‘kuda-kudaan’ yang bisa dinaiki dan berputar dalam sebuah platform datar. Biasanya pada saat pemutaran diiringi dengan musik. Sebuah komedi putar biasanya ditemukan dalam taman bermain atau taman tema.
Malahan, kemiripannya cukup identik, perbedaanya ada pada Marry Go Round berupa benda fisik, sedangkan pemira adalah ‘benda’ realitas intersubjektif. Keduanya sama-sama atraksi.
Pemira adalah atraksi yang menampilkan praktik demokrasi, idealisme mahasiswa dan intelektualisme sebagai kuda-kudaan, bentuk kepalsuan dramaturgis untuk menaiki jabatan dan kekuasaan. Hanya berputar, tidak pernah ada warna baru, yang ada hanya replikasi. Datar karena tidak pernah ada peningkatan kualitatif.
Pemira tidak kalah diiringi oleh musik-musik, sayangnya daripada menyegarkan telinga justru malah memuakan. Musik itu adalah perdebatan kosong antar calon, yang seringkali jelas terlihat manuskriptis. Juga sorak-sorai para penggarap ‘jalur undangan’.
Berada di taman bermain yang bernama universitas, di dalamnya ada berbagai macam simulasi dan atraksi. Selain pemira ada wahana atraktif bernama pemberian gelar honoris causa, ada wahana bernama Scopus, dan segudang wahana yang tidak hanya tidak lucu, tapi juga menghina nalar publik!
So guys, let’s play Marry Go Round Pemira!
Catatan: opini ini merupakan sikap pribadi dari penulis, bukan merupakan sikap redaksi maupun organisasi.
Daftar Pustaka
Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. New York: Verso.
Komidi Putar. (2021, Juni 14). Di Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. Diakses pada 16:40, November 14, 2021, dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komidi_putar



![Antusias Civitas Akademika dalam menyaksikan penampilan SDGs dari berbagai fakultas dan lembaga, Kamis (12/02/26) [Bintang/Magang BP2M]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_0441-551x431.jpg)
![Rektor Unnes saat menyampaikan sambutan di Lapangan Prof. Dirham, Kamis (12/2) [Husain/BP2M]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_0554.JPG-551x431.jpeg)
![Pembukaan Perdana Acara Pameran Seni Bertajuk ARTBILITY 6 yang Mengusung Tema “Before I Disappear” pada Rabu (11/2/2026) [BP2M/Haidar Ali]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2026/02/cover-551x431.jpg)
![Ilustrasi isu yang menyeret nama BEM KM Unnes [Hanna/BP2M]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2026/01/1-3-551x431.png)
![Ilustrasi mahasiswa yang terjebak burnout akibat tugas [Hanna/BP2M]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2025/12/1-2-551x431.png)
