Oleh: Adinan Rizfauzi*
Mari kita sepakat sejak awal, bahwa semestinya tugas aparat kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Mau tak mau, kita memang harus sepakat soal itu, kendatipun apa yang terjadi di lapangan jauh dari itu semua, kendatipun kabar soal brutalitas aparat kepolisian makin memekakkan telinga dalam hari-hari terakhir.
Pada aksi Darurat Demokrasi menyoal utak-atik RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 22 Agustus 2024 lalu, misalnya, 18 orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit gara-gara terpapar gas air mata dan water canon yang ditembakkan polisi ke arah massa aksi. Empat hari setelahnya, polisi pamer stok gas air mata di Jalan Pemuda Semarang. Sekitar 30-an peserta aksi ditangkap tanpa alasan yang jelas. Yang menjadi korban represi di titik lokasi diperkirakan ada lebih banyak.
Di daerah lain, situasinya tak lebih baik. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan segerombol aparat kepolisian sedang menyeret dan memukuli salah satu mahasiswa. Diketahui, peristiwa tersebut terjadi di Jakarta, yang menggelar aksi dalam waktu yang hampir bersamaan dengan di beberapa daerah lain, termasuk Semarang. Isu yang mereka angkat pun seragam: menolak revisi RUU Pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintahan Jokowi.
Sekilas, perilaku aparat kepolisian dengan menyeret dan memukuli peserta aksi itu lebih mirip perilaku segerombol preman. Hanya saja, yang satu ini pelakunya memakai seragam dinas, secara legal boleh menggunakan senjata, difasilitasi pelindung-pelindung khusus, dan semua-semua itu, ironisnya, ada lantaran pajak warga.
Namun, jangan salah. Di Bandung, aparat kepolisian seperti tak puas dengan fasilitas yang dibeli dari uang rakyat. Mereka diduga menggunakan senjata tambahan: batu. Gara-gara lemparan batu yang datang dari arah barisan polisi, salah seorang peserta aksi mendapat luka serius pada mata sebelah kirinya. Sudah kehilangan hak untuk berpendapat, masih pula terancam kehilangan bola mata.
Sulit mencari pembenar mengenai kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dan memang hanya orang sinting yang menganggap kekerasan oleh aparat boleh dilakukan dengan suka-suka. Sayangnya, dalam beberapa kesempatan, saya kerap mendengar ucapan yang seakan menganggap kekerasan oleh aparat kepolisian adalah suatu hal yang normal dan biasa saja, dengan alasan: “Bukannya para demonstran juga rusuh.” Atau: “Lho, itu kan gara-gara mahasiswa merusak pagar gedung.”
Bagaimanapun, sulit mengkondisikan massa aksi layaknya peserta kegiatan pramuka atau paskibra, dan bagaimanapun, demonstrasi bukan sekedar aksi baris-berbaris. Ini adalah kerumunan yang memendam emosi lantaran terlalu sering diabaikan, dipinggirkan, dan diinjak-injak haknya.
Aksi merobohkan pagar, memaksa merangsek masuk ke halaman gedung pemerintahan, apalagi sekedar membakar ban, hendaknya dipandang dan ditangani dengan tak berlebihan layaknya menghadapi musuh di medan perang. Dalam demonstrasi, ketidaktertiban menang hal yang lumrah, kalau tidak boleh dibilang perlu.
Toh, tidak ada jaminan kalau kegiatan yang selama ini dianggap tertib sepenuhnya berdampak baik. Rapat yang diselenggarakan Badan Legislasi DPR pada Rabu, 21 Agustus 2024 lalu adalah salah satu contohnya (hasil rapat Baleg DPR tersebut batal ketok palu di rapat paripurna setelah adanya demonstrasi di beberapa kota). Walaupun para anggota dewan menggelar rapat dengan tertib, tidak merusak fasilitas umum, bahkan tanpa teriakan penolakan yang berarti dari fraksi yang terlibat, dampak dari rapat itu bisa sangat berbahaya, terutama bagi sistem demokrasi.
Betapa tidak, rapat Baleg DPR yang berlangsung hanya tujuh jam itu berusaha memelintir putusan Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga tinggi negara yang putusannya bersifat final dan mengikat, sesuai kepentingan mereka-mereka sendiri. Apa yang dilakukan DPR dan diamini pemerintah itu sejatinya merupakan upaya manipulasi konstitusional. Sejarah mencatat praktik-praktik semacam itu bakal membubarkan demokrasi dengan cepat.
Steven Levitsky dan Daniel Ziblat dalam buku Bagaimana Demokrasi Mati menjelentrehkan betapa pemimpin otoriter bisa saja membajak sistem demokrasi dengan cara yang tampak legal. Sebab, kebijakan yang ada tetap dibuat melalui mekanisme demokrasi, meski lembaga-lembaga demokrasi yang ada sudah berhasil dikendalikan oleh “sang demagog”. Situasi tersebut bisa makin menjadi-jadi ketika partai politik gagal menjalankan perannya sebagai penjaga gerbang demokrasi lewat seleksi kandidat peserta pemilu dengan tetap mengusung individu yang memiliki kecenderungan otoriter.
Dari segi manapun, perusakan pagar atau fasilitas-fasilitas lain oleh massa aksi jelas tak ada apa-apanya jika dibandingkan perilaku ugal-ugalan para pejabat yang berniat membajak sistem demokrasi. Karena itulah, apa-apa yang dilakukan oleh massa pada aksi Darurat Demokrasi kemarin semestinya tidak sedikit pun boleh dijadikan pembenar atas praktik kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Maka, yang menjadi penting adalah jangan pernah sekalipun menormalisasi kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian. Sekali saja kekerasan itu dianggap normal, yang terjadi selanjutnya adalah kekerasan-kekerasan yang tak berkesudahan. Lingkaran setan makin terbentuk dengan adanya praktik impunitas. Jika sudah begitu, siapa lagi yang akan menjadi korban kalau bukan warga biasa seperti kita.
Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat barangkali bukanlah tugas yang mudah. Belum lagi, jika itu dilakukan oleh lembaga yang berisi orang-orang malas–untuk mengingat kembali sebuah coretan di tembok itu: rajin baca jadi pintar, malas baca jadi polisi.
Mari selamanya mengutuk kekerasan demi kekerasan oleh aparat kepolisian, betapapun muak dan melelahkan.
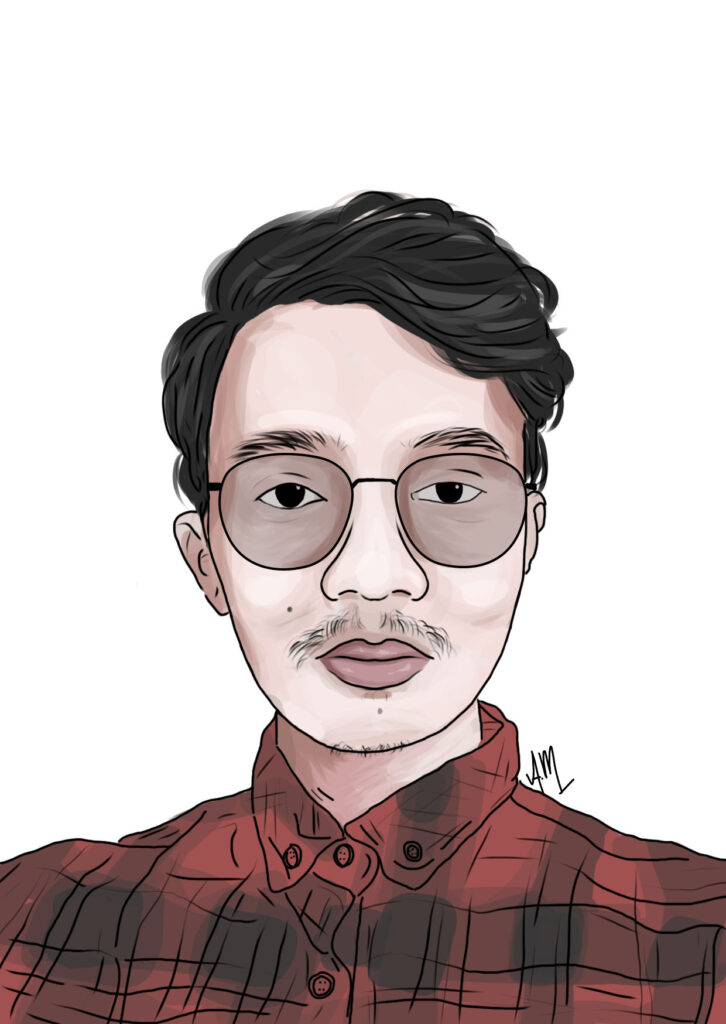
*Mahasiswa Ilmu Politik 2020
Catatan: opini ini merupakan sikap pribadi penulis, bukan sikap redaksi maupun organisasi.