Sekali dalam sepekan, wanita tua itu selalu menghidangkan semangkuk sop iga panas di atas meja tanpa pernah disentuhnya. Asap tipis yang mengepul keluar dari mangkuk itu, ia biarkan menguar lalu hilang dengan sendirinya. Di balik tudung saji bernuansa biru laut itu, ia menyimpannya. Menyimpannya bersama dengan harapan yang selalu ia simpan rapi di relung hatinya paling dalam. Ia masih percaya bahwa suatu hari seorang yang ia nanti itu akan datang. Sayangnya, hari itu tidak pernah datang. Sementara sop iga yang ia racik sepenuh hati itu dibiarkan tak terjamah sampai berhari-hari.
Aku menyaksikan Bu Ning masih sibuk beradu dengan alat-alat masak di dapur. Ia mengeluarkan bahan-bahan membuat sop iga dari dalam kantong plastik dengan hati-hati. Seperti biasa setiap Sabtu, aku berangkat ke pasar lalu pulang menenteng sekantong plastik isi daging dengan kualitas nomer satu. Sehingga tidak ada lagi alasan, untuk ia selalu mengeluh karena dagingnya susah untuk ditelan.
Ini sudah kesekian kalinya, hampir tak bisa terhitung lagi. Sop iga yang dibuatnya itu harus berakhir di tempat sampah. Ia tidak akan membiarkan seorangpun menyentuhnya tanpa seizin darinya. Bu Ning selalu membuatnya dalam satu porsi mangkuk ukuran sedang. Tidak kurang, tidak lebih. Ketika esok kembali datang, ia sudah tidak peduli lagi dengan sop itu. Pada pekan berikutnya, ia pasti akan melakukan hal yang sama.
Bu Ning mulai mengiris bawang dan rempah-rempah lainnya ketika aku mengintipnya dari balik pintu. Tangannya masih terlihat cekatan dan lihai memainkan pisau-pisau dapur nan tajam itu. Kemampuannya dalam menghidupkan aroma masakan masih tak terkalahkan. Meskipun usianya sudah terlalu senja untuk urusan dapur tapi Bu Ning masih tetap jadi yang terbaik.
“Sudah jangan ndelik di sana, sini kalau mau lihat,” ujar Bu Ning kemudian yang rupanya menyadari kehadiranku.
Seperti maling yang sedang tertangkap basah, aku hanya meringis sambil menggaruk-garuk tengkukku yang rasanya tentu saja tidak gatal.
“Ada yang bisa saya bantu?” tanyaku basa basi.
Sebenarnya aku sendiri sudah tahu jawabannya. Wanita itu paling tidak suka ada yang merecokinya ketika memasak. Apalagi untuk urusan kali ini, ia ingin membuatnya dengan tangan sendiri. Katanya untuk orang yang spesial, maka harus dibuat dengan cara yang spesial pula. Apapun yang berasal dari hati, pasti akan menciptakan cita rasa yang berbeda. Itu yang selalu Bu Ning katakan padaku.
Bu Ning masih tak kunjung menjawab. Tidak menerima, menolak, tidak salah satunya. Ia masih sibuk merebus tulang-tulang dalam panci presto di atas tungku api yang membara. Sepertinya aku harus segera beranjak dari dapur setelah aku tahu kehadiranku tidak terlalu dibutuhkan disini.
“Mau pergi kemana? Kupas kentangnya.”
Mataku melebar. Apakah aku tidak salah dengar?. Bu Ning mengizinkanku membantunya. Aku mengambil beberapa buah kentang untuk kucuci lalu memotongnya dadu. Pandanganku masih tak bisa lepas dari sosok wanita yang berdiri di depan tungku api itu. Meskipun ia tak betah berdiri lama-lama, ia cukup telaten memeriksa daging yang ia masak itu.
“Kalau aku sudah tidak memasak lagi,” Bu Ning mulai berdialog.
Aku masih menunggunya. Menunggu setiap kata yang akan keluar dari mulutnya.
“Kamu bisa menggantikanku membuatkan sop iga buat Yanti,” lanjutnya. “Dia suka sekali sop iga yang masih panas, daging yang empuk, dengan sedikit sayuran.”
“I-iya,” kataku sambil memotong dadu kentang-kentang itu.
Baca Juga Cerpen : Seorang Lelaki yang Ingin Sendiri
Mengenai Yanti, orang yang selalu Bu Ning ceritakan, aku hapal betul. Setiap sore ketika aku ajak Bu Ning bersantai di depan beranda rumah, ia tak pernah berhenti bercerita. Dari ceritanya aku simpulkan bahwa Yanti adalah anak semata wayangnya yang kini bekerja di luar kota. Setiap Sabtu dalam sepekan, perempuan itu akan pulang ke rumah mengunjungi ibunya. Ritual yang tak pernah terlupa, Bu Ning akan selalu menyajikan sop iga panas kesukaannya. Sop iga yang selalu ia simpan di balik tudung saji berenda itu.
Sayangnya Bu Ning tak pernah sadar akan hal itu. Kenyataan yang ada selalu berbanding terbalik dengan harapannya. Ia terbunuh dengan harapannya sendiri. Lagi-lagi, wanita tua itu menggantungkan harapan yang salah. Bu Ning terlalu rapuh untuk ingat apa yang sebenarnya terjadi. Yanti tidak akan pernah datang. Sementara sop iganya akan dingin dengan sendirinya sebab perempuan itu tidak akan pernah ada untuk memakannya.
Setelah berjam-jam menunggu tulang iga itu empuk, Bu Ning akhirnya mendapatkan semangkuk sop iga panas. Sop iga untuk Yanti yang ia buat dengan sepenuh hati. Seperti biasa, mangkuk itu kini ia letakkan di atas meja makan. Sebelum menutupnya dengan tudung saji, ia memandanginya cukup lama.
“Hari ini Yanti pasti datang dan menghabiskannya.”
Bu Ning lalu kembali ke kamarnya bersamaan dengan aroma sop iga yang masih kental terasa. Aku menaikkan selimut Bu Ning. Ia sepertinya kelelahan setelah seharian ada di dapur. Kerutan di wajahnya sudah kentara sekali. Rambutnya hampir memutih dengan sempurna. Sementara Alzhaimer sudah lama diidapnya selama setahun terakhir. Penyakit yang menyerang memori di otaknya.
Wanita itu seringkali bertingkah sesuatu yang tak pernah aku mengerti. Ia seringkali mengada-ada sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya. Sampai akhirnya ketakutan terbesarku datang juga. Bu Ning mengada-ada tentang aku. Ibuku menggantiku dengan Yanti. Lalu mengada-ada cerita bahwa aku sedang berada di negeri antah berantah dan akan pulang setiap hari Sabtu. Ibuku menjadikan orang lain sebagai anak semata wayangnya. Sementara aku malah dijadikan orang lain oleh ibuku sendiri.
Bu Ning sudah tertidur, aku kembali ke ruang makan tempat dimana sop iga itu disimpan. Uap itu masih mengepul dengan sempurna, hidungku menghidu aroma rempah-rempah yang sangat kentara. Mulai saat ini, aku akan mulai menjadi Yanti. Yanti yang menyukai sop iga panas, anak semata wayang Bu Ning yang sedang bekerja di luar kota. Karena sebenarnya Yanti memang tidak pernah ada. Tidak akan pernah.
Penulis : Syifa Amalia
Editor : Rona Ayu Meivia

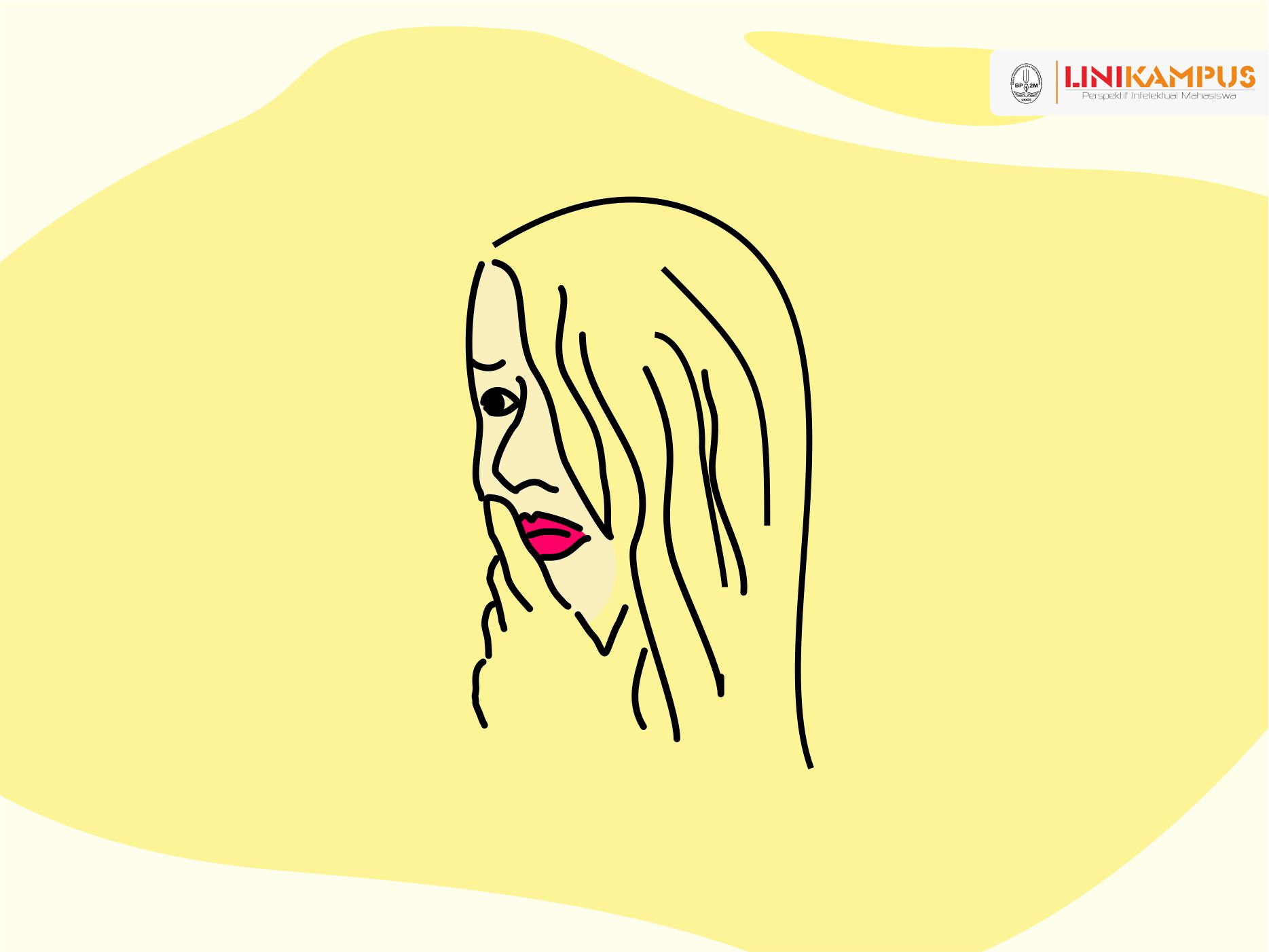
![Mahasiswa Unnes sebagai narator drama panggung terbuka Ruwat Rawat PGSD pada, (23/02/2026) [Muhammad Rayhan Nova/Magang BP2M]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-24-at-12.09.49-551x431.jpeg)
![Antusias Civitas Akademika dalam menyaksikan penampilan SDGs dari berbagai fakultas dan lembaga, Kamis (12/02/26) [Bintang/Magang BP2M]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_0441-551x431.jpg)
![Rektor Unnes saat menyampaikan sambutan di Lapangan Prof. Dirham, Kamis (12/2) [Husain/BP2M]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG_0554.JPG-551x431.jpeg)
![Pembukaan Perdana Acara Pameran Seni Bertajuk ARTBILITY 6 yang Mengusung Tema “Before I Disappear” pada Rabu (11/2/2026) [BP2M/Haidar Ali]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2026/02/cover-551x431.jpg)
![Ilustrasi isu yang menyeret nama BEM KM Unnes [Hanna/BP2M]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2026/01/1-3-551x431.png)
![Ilustrasi mahasiswa yang terjebak burnout akibat tugas [Hanna/BP2M]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2025/12/1-2-551x431.png)