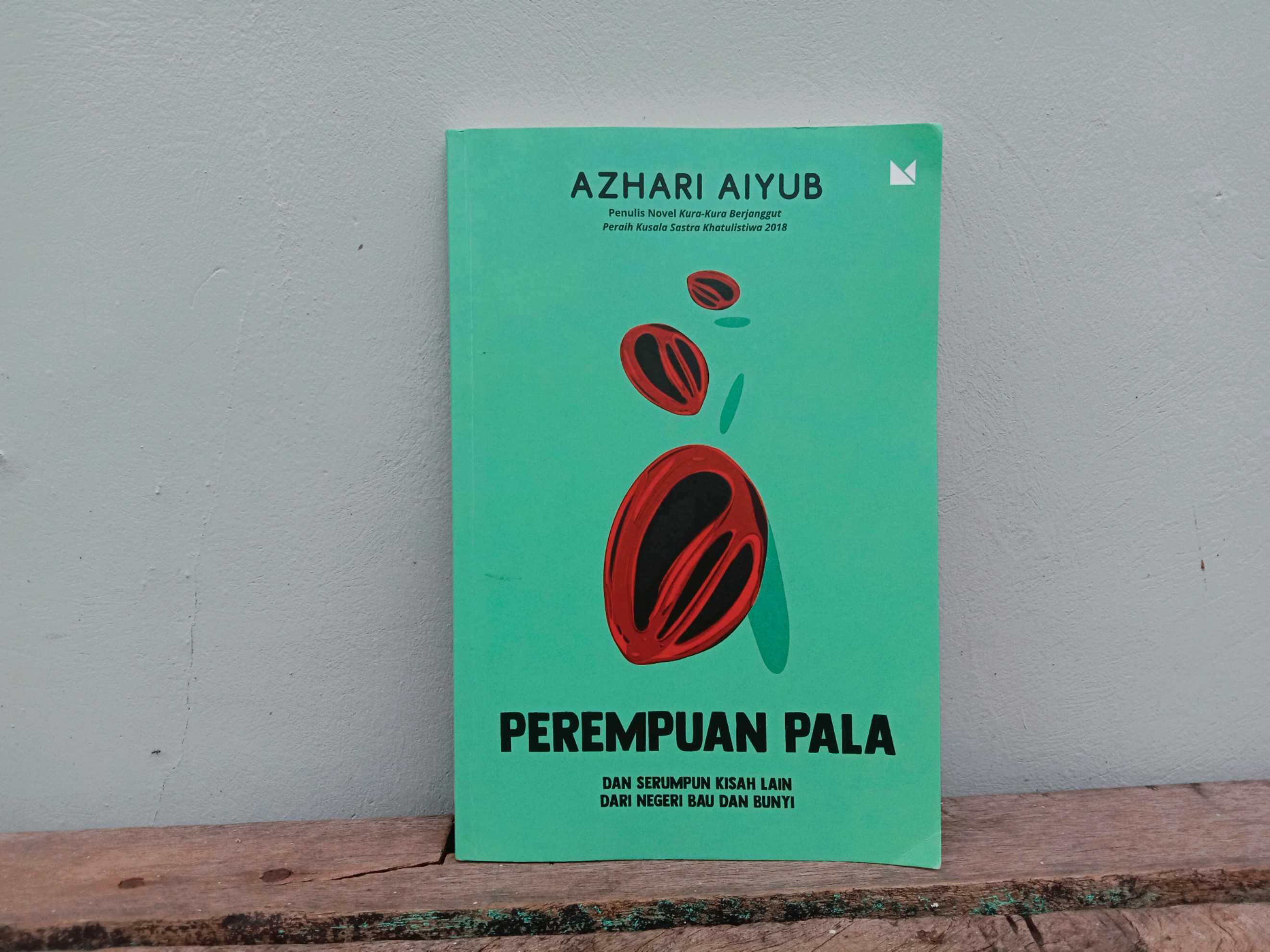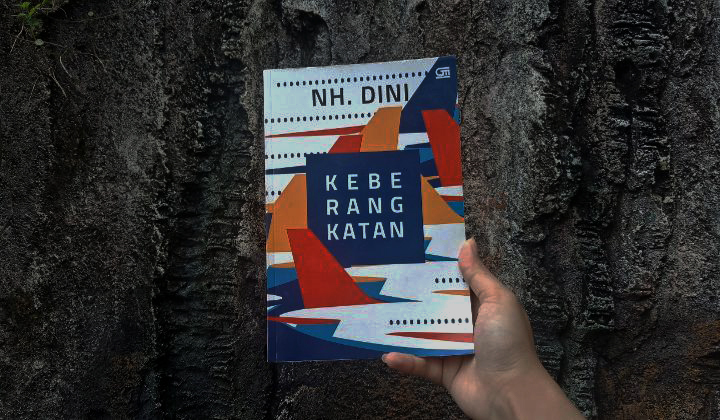Senja,
secara etimologis berasal dari bahasa Sansekerta sandhya, yang “berarti saat matahari baru terbenam”. Kata senja
semakin kuat oleh simbol-simbol kebendaan yang melekat padanya. Secara definisi simbolik,
senja diwakili oleh adanya benda berupa matahari yang tengah atau akan terbenam. Dalam entitas wilayah religius, senja bisa diasosiasikan dengan
maghrib—waktu saat adzan sholat tiga rakaat dikumandangkan.
secara etimologis berasal dari bahasa Sansekerta sandhya, yang “berarti saat matahari baru terbenam”. Kata senja
semakin kuat oleh simbol-simbol kebendaan yang melekat padanya. Secara definisi simbolik,
senja diwakili oleh adanya benda berupa matahari yang tengah atau akan terbenam. Dalam entitas wilayah religius, senja bisa diasosiasikan dengan
maghrib—waktu saat adzan sholat tiga rakaat dikumandangkan.
Dibangun
oleh kekuatan kelompok yang dominan, senja kerap kali tidak akrab di telinga
daripada kata maghrib untuk merepresentasikan kondisi matahari terbenam. “Sudah
maghrib, ayo pulang” jauh lebih terasa nyaman di telinga daripada penggunaan, “Sudah
senja, ayo pulang”. Senja mewakili mozaik kecil di antara dua waktu besar sekaligus
sebagai jembatan yang menghubungkan peralihan waktu siang ke waktu malam. Maghrib
sebagai ruang kontemplasi masyarakat muslim untuk bertemu Tuhannya di pakai
sebagai pengganti senja yang agaknya kurang begitu akrab di masyarakat yang
didominasi oleh Muslim.
oleh kekuatan kelompok yang dominan, senja kerap kali tidak akrab di telinga
daripada kata maghrib untuk merepresentasikan kondisi matahari terbenam. “Sudah
maghrib, ayo pulang” jauh lebih terasa nyaman di telinga daripada penggunaan, “Sudah
senja, ayo pulang”. Senja mewakili mozaik kecil di antara dua waktu besar sekaligus
sebagai jembatan yang menghubungkan peralihan waktu siang ke waktu malam. Maghrib
sebagai ruang kontemplasi masyarakat muslim untuk bertemu Tuhannya di pakai
sebagai pengganti senja yang agaknya kurang begitu akrab di masyarakat yang
didominasi oleh Muslim.
 |
| zomplanksuryana.blogspot.com |
Waktu maghrib
ditangkap secara baik, diolah secara sempurna dan disajikan dengan ringan untuk
memperlihatkan secara gamblang lapisan-lapisan kehidupan sosial di waktu yang
singkat. Salman Aristo, seorang penulis skenario yang punya segudang pengalaman
di dunia perfilman membangun cerita yang menarik dengan mengasosiasi waktu
maghrib dan kehidupan sosio kultural kota nomor wahid di Indonesia, Jakarta. Aristo
berusaha menangkap maghrib bukan sebagai fenomena religius semata namun sebagai sebuah
konsep setting waktu yang menjadi basic penting dalam lima tautan cerita
yang digarapnya untuk menyampaikan suatu pesan sekaligus realitas mengenai Jakarta.
ditangkap secara baik, diolah secara sempurna dan disajikan dengan ringan untuk
memperlihatkan secara gamblang lapisan-lapisan kehidupan sosial di waktu yang
singkat. Salman Aristo, seorang penulis skenario yang punya segudang pengalaman
di dunia perfilman membangun cerita yang menarik dengan mengasosiasi waktu
maghrib dan kehidupan sosio kultural kota nomor wahid di Indonesia, Jakarta. Aristo
berusaha menangkap maghrib bukan sebagai fenomena religius semata namun sebagai sebuah
konsep setting waktu yang menjadi basic penting dalam lima tautan cerita
yang digarapnya untuk menyampaikan suatu pesan sekaligus realitas mengenai Jakarta.
Cerita pertama
menggambarkan kehidupan Iman yang dimainkan oleh Indra Birowo. Iman yang bekerja
sebagai seorang satpam selalu dituntut untuk pergi kerja pagi dan pulang sore. Setelah
sampai di rumah, ia disambut jerit tangis anaknya yang masih berumur beberapa
bulan. Di sebuah kamar bersama Nur—istrinya—Iman merengek meminta jatah waktu
untuk menyatukan lahir dan batin bersama istrinya yang telah tiga hari
dihambat lembur kerja. Namun maghrib menjadi rival yang menggagalkan hasrat Iman
menggauli istrinya yang membuat Iman muntab.
menggambarkan kehidupan Iman yang dimainkan oleh Indra Birowo. Iman yang bekerja
sebagai seorang satpam selalu dituntut untuk pergi kerja pagi dan pulang sore. Setelah
sampai di rumah, ia disambut jerit tangis anaknya yang masih berumur beberapa
bulan. Di sebuah kamar bersama Nur—istrinya—Iman merengek meminta jatah waktu
untuk menyatukan lahir dan batin bersama istrinya yang telah tiga hari
dihambat lembur kerja. Namun maghrib menjadi rival yang menggagalkan hasrat Iman
menggauli istrinya yang membuat Iman muntab.
Cerita kedua
tentang seorang preman kampung yang masih dibekap mabuk semalam. Berjalan di
depan mushola dan mampir ke warung seorang Kiai penjual kerupuk. Preman tersebut tak habis pikir, mengapa masih banyak orang terus
menyumbang masjid namun tidak pernah hadir ketika Tuhan memanggil. Tambah bingung
pula preman tersebut ketika mendengar apa yang menjadi kesenangan hidup sang Kiai
yang tampak lemah dan letih. “Adzan di mushola”.
tentang seorang preman kampung yang masih dibekap mabuk semalam. Berjalan di
depan mushola dan mampir ke warung seorang Kiai penjual kerupuk. Preman tersebut tak habis pikir, mengapa masih banyak orang terus
menyumbang masjid namun tidak pernah hadir ketika Tuhan memanggil. Tambah bingung
pula preman tersebut ketika mendengar apa yang menjadi kesenangan hidup sang Kiai
yang tampak lemah dan letih. “Adzan di mushola”.
Cerita
ketiga mengenai pertemuan para penghuni di sebuah kompleks rumah. Mereka yang
sudah hidup dan tinggal di kompleks rumah tersebut selama bertahun-tahun tidak
pernah mengenal sebelum suatu insiden kecil akhirnya mempertemukan para
penghuni kompleks. Momen menunggu Aki—penjual nasi goreng langganan orang-orang
kompleks rumah tersebut—membuat mereka duduk dalam satu tempat yang sama,
setara dan memulai obrolan pertama mereka setelah bertahun-tahun hidup dalam
gua individualitas. Menanggalkan baju status sosial mereka yang bekerja sebagai
apa dan di mana.
ketiga mengenai pertemuan para penghuni di sebuah kompleks rumah. Mereka yang
sudah hidup dan tinggal di kompleks rumah tersebut selama bertahun-tahun tidak
pernah mengenal sebelum suatu insiden kecil akhirnya mempertemukan para
penghuni kompleks. Momen menunggu Aki—penjual nasi goreng langganan orang-orang
kompleks rumah tersebut—membuat mereka duduk dalam satu tempat yang sama,
setara dan memulai obrolan pertama mereka setelah bertahun-tahun hidup dalam
gua individualitas. Menanggalkan baju status sosial mereka yang bekerja sebagai
apa dan di mana.
Cerita keempat
diisi tokoh bernama Ivan, seorang anak kecil yang membolos sekolah lalu pergi
ke tempat rental Play Station di
waktu menjelang maghrib. Mitos selalu diperdengarkan oleh anak-anak sebagai
bahan ancaman orang tua agar anak taat pada perintah. Mitos maghrib yang banyak
dihuni kuntilanak pemangsa anak dan setan-setan pun menjadi asupan imaji
anak-anak tanpa mengenal batas wilayah. Tidak pula hanya di desa, bahkan di
Jakarta, mitos setan yang banyak berkeliaran di waktu maghrib juga mendiami
isi kepala anak-anak Jakarta.
diisi tokoh bernama Ivan, seorang anak kecil yang membolos sekolah lalu pergi
ke tempat rental Play Station di
waktu menjelang maghrib. Mitos selalu diperdengarkan oleh anak-anak sebagai
bahan ancaman orang tua agar anak taat pada perintah. Mitos maghrib yang banyak
dihuni kuntilanak pemangsa anak dan setan-setan pun menjadi asupan imaji
anak-anak tanpa mengenal batas wilayah. Tidak pula hanya di desa, bahkan di
Jakarta, mitos setan yang banyak berkeliaran di waktu maghrib juga mendiami
isi kepala anak-anak Jakarta.
Cerita kelima
menggambarkan bagaimana rumitnya hubungan asmara dua sejoli yang sudah menjalin
hubungan selama tujuh tahun. Dibalut jalanan kampung yang padat, pasangan
tersebut terlibat adu mulut di sepanjang perjalanan mereka yang dituntut harus sampai
di tempat pernikahan kerabatnya sebelum maghrib. Dengan sub judul, “Jalan
Pintas”, laki-laki yang diperankan aktor kawakan Indonesia, Reza Rahardian
mengambil jalan pintas untuk sampai di tempat tujuan. Dipenuhi dengan debat
mengenai tanggung jawab menikah dan konflik dengan warga terkait jalan, plot
ini terasa ingin menyampaikan pesan bahwa menikah menjadi suatu yang harus
dicapai sekaligus dihindari dalam waktu bersamaan.
menggambarkan bagaimana rumitnya hubungan asmara dua sejoli yang sudah menjalin
hubungan selama tujuh tahun. Dibalut jalanan kampung yang padat, pasangan
tersebut terlibat adu mulut di sepanjang perjalanan mereka yang dituntut harus sampai
di tempat pernikahan kerabatnya sebelum maghrib. Dengan sub judul, “Jalan
Pintas”, laki-laki yang diperankan aktor kawakan Indonesia, Reza Rahardian
mengambil jalan pintas untuk sampai di tempat tujuan. Dipenuhi dengan debat
mengenai tanggung jawab menikah dan konflik dengan warga terkait jalan, plot
ini terasa ingin menyampaikan pesan bahwa menikah menjadi suatu yang harus
dicapai sekaligus dihindari dalam waktu bersamaan.
Waktu maghrib
menjadi representasi pas untuk menggambarkan persoalan-persoalan mendasar di Jakarta.
Tak perlu berbicara mengenai carut marutnya Jakarta dalam konteks masalah yang
besar, masalah-masalah sederhana macam anak membolos sekolah, individualisme,
tingkat relijius yang rendah, hingga konflik plural dan kepentingan di masyarakat
kecil Jakarta sudah cukup menjadi penanda bahwa Jakarta tak selamanya
bersahabat. Ada masalah yang jauh lebih urgent dari sekadar ingin berduit
banyak. Kebahagiaan selalu sukar dirajut di tengah banyaknya idealisme
kepentingan dari setiap manusia yang mendiami Jakarta, mulai dari yang hanya
hidup di gang kecil, terpinggirkan, dan jauh dari kesan mewah hingga manusia
yang hidup di puncak apartemen mahal, bermobil mewah dan berstatus sosial
tinggi.
menjadi representasi pas untuk menggambarkan persoalan-persoalan mendasar di Jakarta.
Tak perlu berbicara mengenai carut marutnya Jakarta dalam konteks masalah yang
besar, masalah-masalah sederhana macam anak membolos sekolah, individualisme,
tingkat relijius yang rendah, hingga konflik plural dan kepentingan di masyarakat
kecil Jakarta sudah cukup menjadi penanda bahwa Jakarta tak selamanya
bersahabat. Ada masalah yang jauh lebih urgent dari sekadar ingin berduit
banyak. Kebahagiaan selalu sukar dirajut di tengah banyaknya idealisme
kepentingan dari setiap manusia yang mendiami Jakarta, mulai dari yang hanya
hidup di gang kecil, terpinggirkan, dan jauh dari kesan mewah hingga manusia
yang hidup di puncak apartemen mahal, bermobil mewah dan berstatus sosial
tinggi.
Kehidupan sosio-kultural
masyarakat di Jakarta juga menginterpretasi sebuah pesan tentang bagaimana
maghrib menjadi waktu yang dimaknai secara berbeda oleh tiap manusia. Kelas
bawah memandang maghrib sebagai momen religius, kelas menengah menganggap
maghrib sebagai jam pulang, kelas atas mengartikan maghrib sebagai waktu
memulai berpesta. Anak-anak merasakan maghrib sebagai datangnya setan-setan
yang akan memakan mereka, remaja menjadikan maghrib sebagai waktu untuk
berkontemplasi, orang dewasa mengartikan maghrib sebagai ruang bercengkrama dengan
pasangan, dan orang tua menyerap maghrib sebagai waktu bersimpuh di hadapan
Tuhan.
masyarakat di Jakarta juga menginterpretasi sebuah pesan tentang bagaimana
maghrib menjadi waktu yang dimaknai secara berbeda oleh tiap manusia. Kelas
bawah memandang maghrib sebagai momen religius, kelas menengah menganggap
maghrib sebagai jam pulang, kelas atas mengartikan maghrib sebagai waktu
memulai berpesta. Anak-anak merasakan maghrib sebagai datangnya setan-setan
yang akan memakan mereka, remaja menjadikan maghrib sebagai waktu untuk
berkontemplasi, orang dewasa mengartikan maghrib sebagai ruang bercengkrama dengan
pasangan, dan orang tua menyerap maghrib sebagai waktu bersimpuh di hadapan
Tuhan.
Salman
Aristo dan film Jakarta Maghrib seperti sebuah teori hasil pemikiran dan cara
pandangnya tentang Jakarta. Hanya sebatas penanda dan pengingat. Entah ingin dijadikan
sebagai bahan hiburan semata, sekadar cerita pengantar tidur, atau sebagai
sebuah bahan refleksi diri. Itu adalah hak penikmat film ini. Yang pasti,
Salman telah berkreasi, mencurahkan gagasan dalam film ini sebagai penanda dan
pengingat. Hanya sebatas itu, sesederhana itu, dan hanya sesingkat itu. Seperti
senja yang hanya sebatas menjadi jembatan singkat dan sederhana antara malam
dan siang. Tidak lebih dan tidak kurang.
Aristo dan film Jakarta Maghrib seperti sebuah teori hasil pemikiran dan cara
pandangnya tentang Jakarta. Hanya sebatas penanda dan pengingat. Entah ingin dijadikan
sebagai bahan hiburan semata, sekadar cerita pengantar tidur, atau sebagai
sebuah bahan refleksi diri. Itu adalah hak penikmat film ini. Yang pasti,
Salman telah berkreasi, mencurahkan gagasan dalam film ini sebagai penanda dan
pengingat. Hanya sebatas itu, sesederhana itu, dan hanya sesingkat itu. Seperti
senja yang hanya sebatas menjadi jembatan singkat dan sederhana antara malam
dan siang. Tidak lebih dan tidak kurang.
Muhammad Irkham Abdussalam
Mahasiswa yang galau karena prota, promes, probul, dan proming PPL belum kelar sama sekali.
Mahasiswa yang galau karena prota, promes, probul, dan proming PPL belum kelar sama sekali.

![Penampilan Hanifah Ainurohmah, pemeran Kartini dalam drama “Kartini” di Malam Puncak Peringatan Hari Chairil Anwar 2024, Minggu (12/5). [BP2M/Muhamad Sopian]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2024/05/IMG_2902-scaled.webp)
![Mahasiswa geram wakil rektor tak dapat tandatangani pakta integritas pada Selasa (7/5) [Magang BP2M/Anastasia]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2024/05/1-scaled.webp)