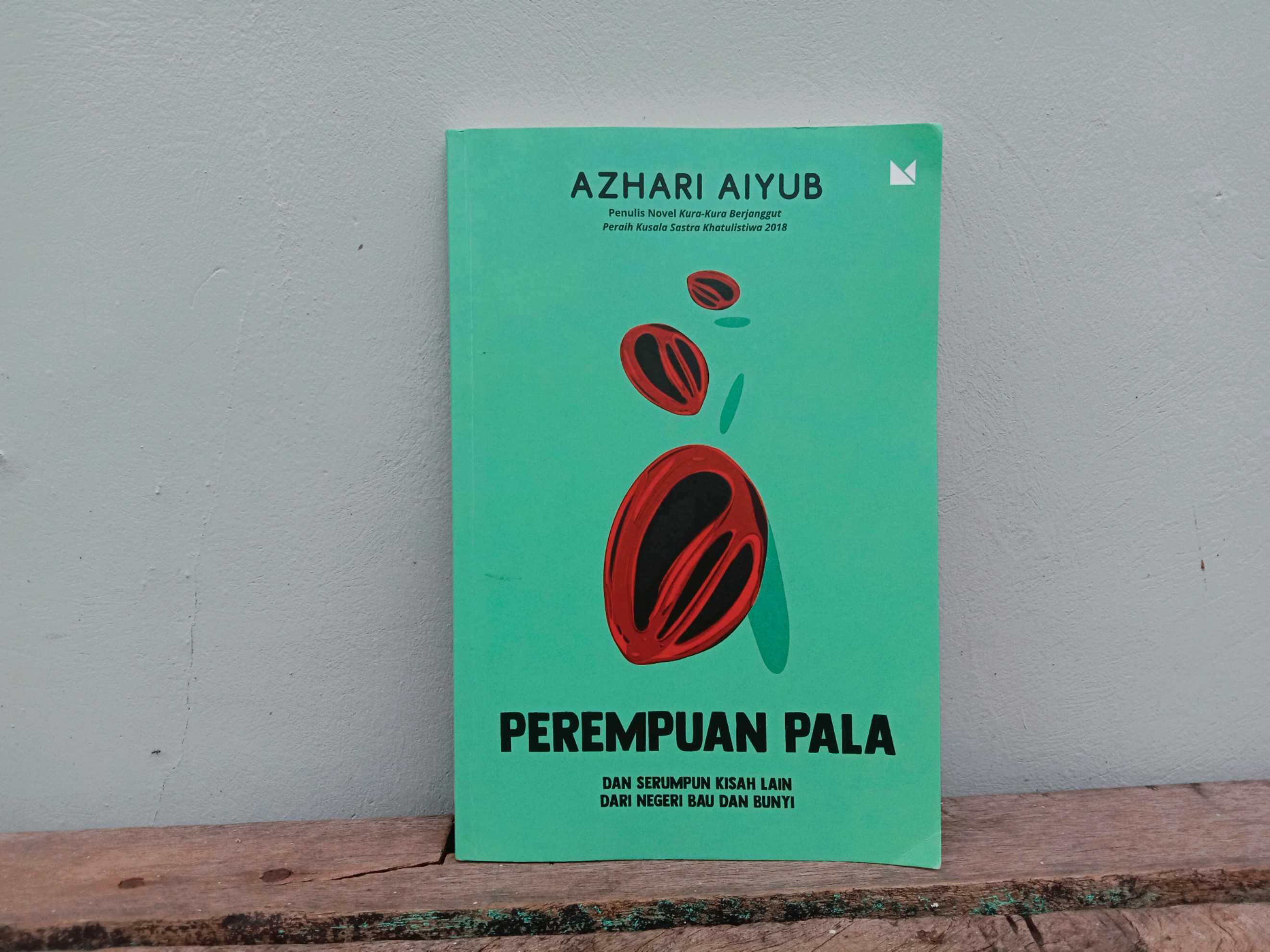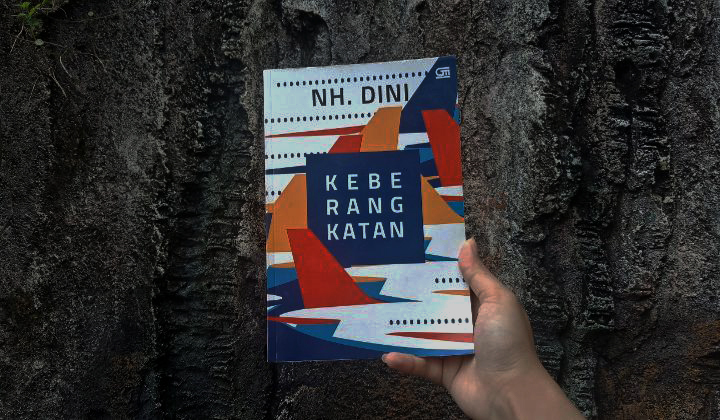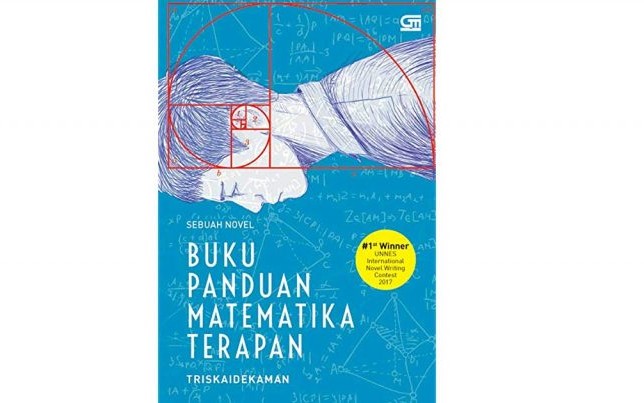|
| Poster film Spotight (2016) |
Barangkali, hanya investigasilah yang mampu menyelamatkan jurnalisme dari krisis kepercayaan masyarakat sekarang. Saat keredaksian media menetapkan liputan investigasi untuk membongkar suatu kasus, di sana ada pertaruhan yang besar. Bertaruh tenaga, pikiran, dana, hingga nyawa. Prinsip bahwa jurnalisme adalah “mata masyarakat” diuji melawan kabut sistematik yang menutup rapat sayatan luka atas kemanusiaan.
Film Spotlight diangkat dari kisah nyata yang digarap oleh sutradara Tom McCarthy. Kasus pelecehan seksual kepada anak yang dilakukan para pemuka gereja tercium para wartawan harian Boston Globe. Spotlight sendiri berasal dari nama rubrik yang dikhususkan memuat berita-berita mendalam di harian tersebut. Berangkat dari pengakuan Patrick McSorley (James LeBlanc), para awak yang membidani rubrik ini bersepakat mengangkat kasus ini ke permukaan.
“Kehidupan keluarga saya susah. Ibu saya tidak berdaya (dengan impitan ekonomi). Lalu suatu hari, pastor itu datang ke rumah kami. Melihatnya datang, seperti melihat tangan Tuhan menolong kami. Suatu hari, ia mengajak saya keluar rumah untuk membeli es krim. Saat itu, usia saya baru 12 tahun. Setelah membeli es krim, di dalam mobil, pastor itu mulai meraba kaki saya. Kemudian meraba kemaluan saya. Saat itu saya sangat takut. Saking takutnya sampai saya tidak sadar, es krim yang saya pegang meleleh di tangan….” ungkap Patrick McSorley.
Spotlight yang dipimpin Walter Robinson (Michael Keaton) bekerja memburu fakta bersama tiga reporter, yakni Sacha Pfeiffer (Rachel McAdams), Michael Rezendes (Mark Rufalo), Marty Baron (Liev Schreiber), dan Matt Carroll (Brian d’Arcy James). Investigasi tak berjalan mudah, sebab otoritas gereja bukan pihak sembarangan. Gereja dipandang sebagai tempat suci nan sakral yang tentu saja bertubrukan dengan tudingan harian tersebut. Banyak pihak yang menyangsikan gereja terlibat tindakan pelecehan seksual kepada anak, sebab selama ini tak ada korban yang berani angkat suara.
Melalui film ini, kita diajak menyangkal pemahaman umum bahwa institusi keagamaan adalah representasi kebajikan di dunia. Mitos dan kepercayaan masyarakat kepada institusi keagamaan nyatanya banyak dijadikan celah untuk bertindak “melawan” perintah Tuhan. Ini terbukti saat para reporter mendatangi satu per satu korban. Mereka, para korban, kebanyakan tak punya keberanian berbicara sebab takut berdosa. Lho!
Dalam kehidupan manusia, agama memiliki dua sisi. Sisi pertama, agama sebagai jalan religius. Kedua, agama sebagai sebuah institusi. Dua sisi itu seringkali dicampuradukkan demi melanggengkan kekuasaan. Religiusitas Tuhan disetarakan dengan institusi yang dikelola manusia sehingga memunculkan satu pemahaman bahwa insitusi agama adalah representasi mutlak religius seseorang.
Kita mudah menemukan, institusi agama seringkali menurunkan fatwa yang diamini banyak orang sebagai role model dalam beragama. Maka, tak heran jika kemudian ada satu produsen jilbab melabeli produknya dengan “halal.” Hal itu dilakukan agar masyarakat menganggap bahwa memakai jilbab berlabel halal sebagai salah satu jalan mencapai religiusitas dan menyapa Tuhan. Haduh!
Meski telah mendulang banyak penghargaan, seperti Piala Oscar 2016, film sebagai medium tak bisa menggambarkan secara utuh proses yang dijalani awak Bosten Globe. Dalam salah satu wawancara eksklusifnya dengan tirto.id (27 September 2016), Walter V. Robinson (yang asli) mengatakan, ada hal-hal yang tak disebutkan dalam film.
“Yang tidak ditunjukkan adalah, kami mencoba mengulik sistem pengadilan. Kami menemui semua pengacara yang pernah menangani kasus pelecehan seksual, semua kasus, jadi bukan hanya yang melibatkan pastor saja. Lalu, kami menemukan 1.500 perkara pelecehan seksual di Boston.” ungkap Walter V. Robinson.
Perlu diketahui, selain banyaknya perkara yang harus diselidik oleh awak reporter yang jumlahnya tak sampai 10 orang itu, pihak Spotlight juga harus membuat database selama tiga pekan. Di film, adegan pembuatan database itu hanya kisaran 1-2 hari saja. Ada pula adegan yang dilebih-lebihkan, juga dikecil-kecilkan. Kita bisa mafhum, film tak bisa lepas dari sentuhan estetis agar bisa menarik emosional penonton ke dalam tiap etape cerita.
Menonton film Spotlight, ditambah membaca wawancara eksklusif dengan sang editor aslinya, memberikan kita gambaran betapa rumitnya proses jurnalistik itu sendiri. Dari satu fakta ke fakta lain, dari satu dokumen ke dokumen lain, dari satu debat redaksi ke debat redaksi yang lain. Tak mudah membongkar kasus besar, apalagi bersitegang dengan otoritas kekuasaan.
Barangkali benar, bahwa “kebenaran” itu berharga mahal. Harganya bisa setara dengan nyawa manusia. Pantas saja, sekarang banyak media dan wartawan memilih menyajikan berita asal-asalan. Tak peduli banal, dangkal, sensual; yang penting laku!
Demi kepraktisan dan kemudahan, berita-berita yang kita konsumsi sama sekali tak mengarah pada kebenaran. Yang ada, berita justru memproduksi perselisihan, kegaduhan, dan pengaburan. Lha iya, siapa yang mau melakukan pertaruhan besar atas nama kebenaran di era yang serba cepat dan tergesa-gesa ini? Lha mbuh!
Zarah Amala
Pemabuk film | Bercita-cita menjadi ibu yang baik
Pemabuk film | Bercita-cita menjadi ibu yang baik

![Film Exhuma [Sumber: Showbox]](https://linikampus.com/wp-content/uploads/2024/06/exhuma-551x431.jpg)